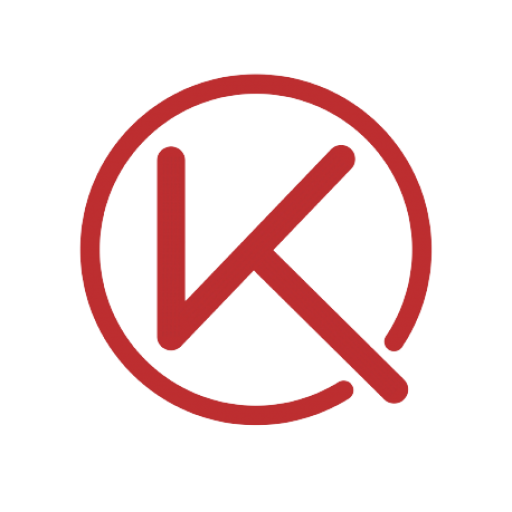Beberapa hari lalu, saya membaca artikel di kicknews.today, sebuah media daring populer di NTB. Kabarnya, Pemerintah Provinsi sedang menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme di NTB.
Pada dasarnya setiap ikhtiar perlindungan anak selalu harus disambut baik. Apalagi yang menyangkut perkembangan mental dan perbuatan melawan hukum. Anak-anak kita memang sudah terlalu jauh masuk dalam spektrum kekerasan. Pergaulan di lingkungan tempat tinggal, tayangan televisi dan media sosial kian mendekatkan anak pada kekerasan. Kita secara tak sadar juga sering ikut mengenalkan kekerasan, melalui pengenalan senjata (meski hanya replika) dalam kegiatan karnaval. Di Indonesia sendiri, pelibatan anak-anak sebagai pelaku langsung dalam tindak kekerasan ekstrem dan teror bahkan sudah terjadi.
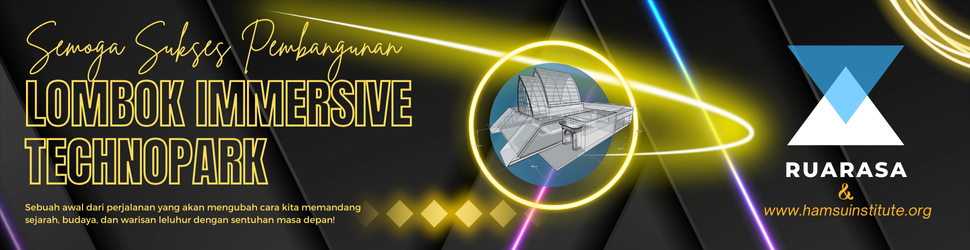
Apakah anak-anak ikut dilibatkan dalam jaringan dan aksi terkait paham kekerasan ekstrem karena mudah untuk didoktrin dan dilatih? Tepatnya, mereka lebih mudah dimanipulasi. Apalagi jika orang tua terutama ibunya juga terlibat. Akan sangat mudah. Anak-anak, bisa dikatakan sangat terpengaruh oleh bimbingan dan asuhan orang tuanya. Potensi mengikuti jejak orang tua setelah dewasa mungkin besar, tapi tentu saja itu juga bergantung pada perkembangan pola pikir dan pengalaman mereka hingga usia dewasa nanti. Sekolah, guru, dan lingkungan pergaulan masih sangat berpeluang mengubah mereka.
Saya pernah ditanya wartawan, apakah anak-anak yang ‘sempat’ terpapar, dapat kembali menjadi seperti pada umumnya yang tidak memiliki paham radikal? Saat itu saya katakan bahwa saya menolak penggunaan istilah radikal/radikalisme yang tidak tepat.
Menurut saya, yang harus hilang dari benak anak-anak ini adalah ekstremisme berbasis kekerasan (violent extremism) serta kedangkalan pikiran atau banalitas kekerasan. Bukan menghilangkan kemampuan untuk menalar atau berfikir mendalam. Masalahnya, program deradikalisasi dan kontraradikalisasi yang diklaim sebagai resep itu justru punya efek samping yang kita khawatirkan di atas.
Lantas apa yang harus diperhatikan agar mereka yang belum maupun yang sempat terpapar menjadi terlindungi? Tentu saja terutama yang harus diperhatikan adalah pergaulannya di sekolah dan relasi sosial di lingkungannya. Karena di sanalah perubahan-perubahan perilaku akan paling mudah tampak.
Kita lihat contoh di Surabaya, salah seorang anak pelaku teror ternyata selama itu di sekolahnya bahkan menolak ikut upacara bendera. Namun, para guru agaknya tak menganggap itu sebagai suatu hal yang perlu dicermati.
Berarti masyarakat turut berperan besar agar anak-anak itu tidak kembali terpapar paham kekerasan ekstrem? Oh jelas. Anak-anak sangat tergantung juga pada pengalaman sosialnya. Jika mereka dikucilkan atau mendapat perlakuan diskriminatif, bukan tidak mungkin kebencian, kedangkalan, dan paham kekerasan ekstrem mereka malah lebih kuat daripada orang tuanya atau siapapun yang menularkannya.
Untuk menyadarkan masyarakat akan hal itu, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sendiri? Ya, pemerintah yang harus memulainya dengan menjadi contoh bagaimana memperlakukan segenap lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Tidak memupuk kebencian dan secara serius meminimalisir kesenjangan (disparitas) paling tidak dalam praktik-praktik layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, maupun dalam aktivitas perekonomian.
Sementara itu, kita juga harus ingat bahwa kualitas hidup di satu wilayah ditandai dengan kenyamanan warganya. Selain soal sanitasi dan potensi bencana (alam maupun non-alam), ketidaktertiban sosial juga menjadi alat ukurnya yang utama.
Sedihnya, aparatur daerah dan penegak keamanan nyaris tak punya pemahaman sosio-kultural yang cukup untuk memfasilitasi disepakatinya ambang batas ketidaktertiban sosial di satu wilayah. Padahal, siapapun yang berada dalam spektrum kekerasan akan selalu berpotensi terpapar. Jika tidak menjadi pelaku, maka ia berpeluang menjadi korban. Bahkan anak-anak kita.
Kembali ke soal rancangan Pergub. Saya kira ada baiknya para perancang juga mengakomodasi sejumlah agenda aksi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme. Perpres itu menurut saya telah menunjukkan pendekatan yang lebih lunak, komprehensif (lintas sektor), partisipatif (masyarakat dan media massa) dan terukur (target, kinerja, capaian) dalam upaya penanggulangan terorisme.
Di sana juga ada istilah baru yang diperkenalkan pada publik dalam ranah pemberantasan terorisme yaitu ekstremisme. Saya sendiri selama bertahun-tahun telah menolak penggunaan istilah radikalisme untuk menggambarkan persoalan terorisme ini secara akademis. Sesuatu yang entah kenapa selama sekian lama seolah enggan digunakan oleh para pemangku penanggulangan terorisme di Indonesia. Padahal dunia internasional dalam beberapa tahun terakhir juga telah menggunakan frasa “violent extremism” untuk menunjuk praktik-praktik terorisme.
Meski sama-sama bisa menghadirkan berbagai bentuk kekerasan, ekstremisme dan radikalisme adalah dua hal yang sangat berbeda. Mestinya dua hal ini tak diadopsi secara serampangan, yang berpotensi mengakibatkan tidak tercapainya itikad baik dan tujuan dari hadirnya peraturan tersebut.
Kondisi campuraduk tersebut menurut saya menjadi salahsatu kelemahan Perpres, dan saya berharap dapat dihindari pada Pergub NTB ini. Karena hal itu menunjukkan belum tercapainya kesepahaman di antara para pemangku penanggulangan terorisme, bahkan ada yang masih ngotot merujuk pada diksi radikalisme yang oleh banyak ahli disebut tak punya cukup pijakan ilmiah.
Persoalan yang juga perlu untuk diatur secara tepat adalah partisipasi masyarakat. Membangun sebuah sistem deteksi dini dan respon cepat masyarakat dalam hal keamanan lingkungan adalah hal penting dalam kerangka pelindungan anak dari paham kekerasan ekstrem (pemerintah: ekstremisme berbasis kekerasan) dan terorisme.
Sayangnya, wujud kampanye dan aksi yang menonjol seringkali adalah bagaimana mendorong masyarakat agar mau dan sigap melapor jika di wilayahnya terdapat situasi dan kondisi yang mengarah pada ekstremisme berbasis kekerasan.
Padahal jika rambu-rambunya tak disiapkan dan disosialisasikan dengan baik, ada kekhawatiran bahwa hal ini akan meningkatkan potensi konflik horisontal dan pelanggaran hak asasi manusia melalui praktik-praktik intoleransi baru, persekusi, bahkan kekerasan berbasis penistaan (blasphemy based violence) di tengah masyarakat. Padahal niat kita adalah melindungi anak-anak dari paham yang keliru dan dari kejahatan teror.
Dalam hal kontra-narasi, ini juga harus dilakukan dengan hati-hati dan tetap bersandar pada prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat. Dalam hal ini saya kira tak perlu secara ambisius mengendalikan informasi, karena hal itu akan berpotensi kontraproduktif di tengah upaya meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik atas kerja-kerja pelindungan anak, penegakan hukum dan demokratisasi.
Saya kira kita semua sepakat bahwa anak-anak kita harus terlindungi. Kekerasan ekstrem dan teror juga harus dapat dihilangkan dari tanah air kita. Namun tentunya kita tak ingin melihat aksi-aksi pelindungan anak dan penanggulangan teror yang lebih menakutkan dan eksesif ketimbang aksi terornya itu sendiri. Semoga Gubernur NTB memahami…
—
Khairul Fahmi, Pemerhati Keamanan Nasional Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), asal Lombok.