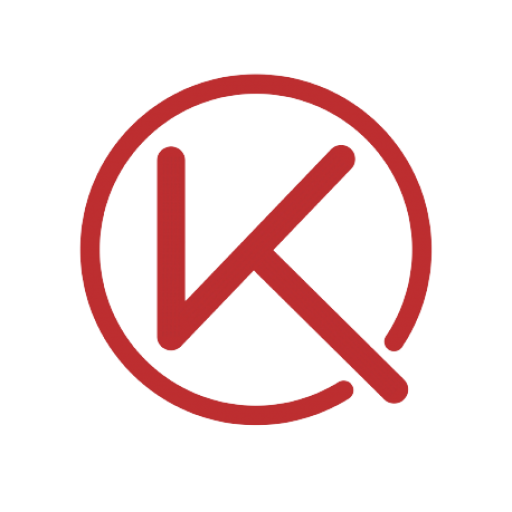Sudah masyhur di kalangan umat Islam, bahwa lailatul qadr adalah malam yang sangat istimewa. Q. S. al-Qadr, menjelaskankanya sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan (sekitar 83 tahun). Ungkapan Al-quran ini dapat dimaknai bahwa keistimewaan lailatul qadr tidak dapat dijelaskan dengan untaian kata karena bersifat ghaib dan berdismensi spritual. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan para malaikat, termasuk Jibril dalam peristiwa ruhaniyah ini.
Untuk memahami hakekat lailatul qadr, perlu dikaji kata “lail” dari terma tersebut. Kata ini dapat dimaknai dalam tiga pengertian yang berbeda; Lafdzî, maknawî, dan majazî (Nazaruddin Umar, 2010). Pertama, perngertian lafdzî (bahasa), kata ini dimaknai sebagai nama waktu, yaitu waktu malam kebalikan dari waktu siang. Waktu ini muncul sebagai dampak dari interaksi antara bumi dan matahari. Perputaran bumi pada porosnya dan dalam mengitari matahari berdampak pada gelapnya sebagian badan bumi. Belahan bumi yang berhadapan langsung dengan matahari mengalami siang, sementara bagian bumi yang membelakanginya akan gelap gulita. Inilah pengertian kata “lail” secara lafdzi. Jika Lailatul qadr, dipahami dalam pengupasan makna kata “lail” seperti itu, berarti peristiwa berdimensi ketuhanan itu hanya bergantung pada interaksi matahari dan bumi. Padahal, Lailatul qadr merupakan kehendak Allah semata dan tak bergantung pada sesuatu di luar diri-Nya, sehingga mustahil Sang Pencipta diatur oleh waktu sebagai makhluk-Nya, .
Kedua, pengertian maknawî. Di sini kata “lail” diterjemahkan sebagai kegelapan, kesunyian, keheningan, dan ketiadaan. Suasana ini merupakan dampak dari ketiadaan cahaya matahari di bagian tertentu pada bumi. Gelapnya bumi nyaris melumpuhkan fungsi indera manusia. Di siang yang terang benderang, melalui kerja indera seseorang dapat menikmati indahnya materi duniawi yang berujung pada hubbud dunyâ (cinta dunia). Sebaliknya, dalam kegelapan, manusia dipaksa berhenti melakukan interaksi dengan alam materi. Situasi gelap seperti ini memungkinkan terjadinya proses pengosongan materi dalam jiwa seseorang. Pada saat bersamaan, muncul perasaan takut dan butuh perlindungan pada Allah, sebagai Dzat memiliki sifat-sifat yang serba Maha luar biasa. Selanjutnya, bersemi dan berkembang pengakuan natural terdahap adanya Dzat Yang Maha Kekal sekaligus dijadikan sebagai satu-satunya tempat berharap dan bergantung.
Disfungsi penglihatan – indera yang paling dominan digunakan — sebagai dampak dari kegelapan, mendorong manusia untuk memaksimalkan fungsi akal dan intuisinya dalam rangka menjaga eksistensinya. Pada tahapan ini, berpotensi tumbuh dalam dirinya sikap bijaksana seiring dengan pemahaman yang lebih konprehensif dan substantif tentang hakekat yang “ada” dibandingkan sebelumnya yang cenderung parsial dan dangkal.
Berdasarkan pengertian kata “lail” yang kedua ini, siapa pun yang berhasil mengosongkan hatinya dari segala bentuk alam materi dan hanya bergantung kepada Allah semata dibarengi dengan maksimalisasi peran akal dan hati dalam menjaga eksistensinya sesungguhnya ia telah mengalami malam meskipun berada di waktu siang. Sebaliknya, individu yang berada di waktu malam tidak dapat mengalami malam yang sesungguhnya jika ia tidak berhasil membebaskan hatinya dari dunia profan dan gagal manfaatkan peran akal (tafakkur) dan hatinya (tadzakkur) sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah.
Ketiga, kata “lail” dalam pengertian Majazî. Di sini, kata tersebut dimaknai kerinduan dan kecintaan kepada Allah Swt. Dipahami demikian karena seseorang yang memiliki rasa cinta dan rindu kepada Allah rela menghabiskan waktunya, termasuk malam harinya untuk bermunajat kepada-Nya. Core value pengertian majazî adalah suasana hati yang bergelora karena kerinduan dan kecintaannya yang luar biasa kepada Sang Khaliq. Pengertian kata “lail” ini fokus pada hubungan hamba dengan Tuhannya dan berhasil menafikkan alam materi (mem-fana’-kan) termasuk dirinya sendiri. Semua alam materi yang terindera dirasakan hanya sebagai penampakan (tajalli) dari Wujud Sang Ghaib. Rasa cinta yang bergelora dalam hatinya kepada Sang al-Rahman membuat si pemburu cinta Tuhan mati rasa terhadap segala yang berbau duniawi, jiwa kehambaanya tenggelam dalam semesta ke-Esa-anNya. Dalam suasana hati yang demikian, tidak ada logika kalkulasi dalam beribadah. Bukan karena tidak boleh secara hukum syariat, tetapi dirinya sudah berhasil melampaui kalkuasi (beyond calculation) dan logika formal dalam beramal. Doa yang dimohonkan pun stiril dari aroma duniawi. Sebab, dalam dirinya hanya ada Allah, Prinsipnya adalah hatiku adalah singgasana Tuhan (qalbî ‘arsy al-Haq). Karena itu, keinginannya hanya satu bagaimana dirinya maksimal dalam mengaktualisasikan rasa cintanya kepada Yang Maha Suci. Pada tahap ini, mengingat hal yang beraroma duniawi, berdoa untuk mewujudkan mimpi hidup (mewah) duniawi, dan beribadah dengan motivasi dunia dalam ritus malamnya adalah hal-hal yang diyakini dapat menurunkan kualitas mahabbah kepada Allah.
Dalam makna majazî ini, bukanlah mata yang menyaksikan malam, tetapi hati yang mengalaminya. Di sini, malam dimaknai sebagai peristiwa psikis yang murni berdimensi ruhani, bukan kejadian fisik yang berdimensi jasmani. Sejalan dengan nalar ini, qiyam lail berarti ruhani yang bangun dalam ritme jasmani yang bergerak, bukan jasmani yang beribadah disertai dengan kekosongan ruhani. Konsisten dengan logika ini, tidak layak disebut qiyam lail ibadah malam seseorang yang hatinya hanya dipenuhi berhala-berhala dunia dan termotivasi untuk meraih mimpi materialistik. Sebaliknya, ketika hati seorang hamba hanya menjadi “rumah” Allah, sesungguhnya saat itu ia telah mengalami malam, meskipun menurut alam inderawi ia berada di waktu siang.
Tiga pengertian kata “lail” di atas menjadi dasar dalam menkonstruksi pamahaman yang benar tentang hakekat “Lailatul qadr”. Jika term. tersebut dimaknai hanya dengan arti “lail” dalam versi pertama, maka akan muncul banyak persoalan terkait mekanisme terjadinya hal bersifat metafisika tersebut. Misalnya, kondisi yang dialami umat Islam di daerah kutub, yakni kota Norilsk Rusia dan kota Inuvik Kanada (Afif Rahman, “Sambut Ramadhan dengan Kisah-Kisah Masjid di Kutub Utara”,detiktravel,6 Juni 2016), di mana di dua kota tersebut matahari bersinar selama 24 jam. Mengikuti nalar makna “lail” versi pertama, mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mendapati malam yang sangat mulia ini. Logika ini tidak hanya mereduksi universitas Lailatul qadr, tetapi lebih berbahaya lagi adanya kesan bahwa Tuhan bertindak diskriminatif terhadap hamba-hamba-Nya. Lebih-lebih tindakan tidak keberpihakan ini dialami oleh mereka yang menjalani ibadah puasa Ramadlan dalam suhu udara yang sangat ekstrim, yakni 0 derajat sampai dengan -50 derajat celsius, sebuah ujian berat yang harus dihadapi di tengah-tengah mereka menjalankan ajaran-Nya.
Pengertian “lail” dalam versi kedua akan menempatkan Lailatul qadr sebagai peristiwa yang bisa dikaji dengan pendekatan saintifik. Mungkin sebagai suatu konsep pemikiran, ia bisa ditelaah dan dikritisi. Tapi, sebagai satu peristiwa ketuhanan (al-wâqiah al-ilâhiyah), ia hanya dapat diimani. Sebab, kekuatan akal tak mampu menjangkau ke-transendentalan-nya.
Pemahaman “lail” yang ketiga paling memungkinkan sebagai dasar dalam memaknai “Lailatul qadr”. Kata “lail” di sini mengambarkan suasana batin yang sama sekali tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Individu yang mengalaminya hanya merasakan kenikmatan tertinggi yang tiada tara, berupa sentuhan hangatnya cinta dari Sang Ilahi. Bagi individu yang mengalami akan terus berusaha meleburkan jiwa kehambaannya dalam kosmos kasih sayang-Nya melalui sejumlah ibadah yang menggerakkan badannya. Dalam dekapan hangatnya cinta tertinggi ini, seorang hamba tak lagi terbersit motivasi mengejar nilai 1000 bulan atau bahkan bernilai jutaan tahun. Alih-alih mengejar nilai tersebut, meskipun surga dengan segala keindahannya dihidangkan di kelopak mata, sama sekali tak tergoda, dirinya tetap sujud menyerahkan diri secara total kepada Sang Kuasa. Inilah yang disebut Lailatul qadr, peristiwa spritual tertinggi yang sangat bersifat personal.
“Lail” dalam pengertian yang ketiga ini bukanlah peristiwa spritual yang terjadi secara tiba-tiba. Ia merupakan suatu hasil dari serangkaian usaha (ibadah) ritual dan sosial secara khusu’ dan istiqamah dalam rentang waktu yang panjang. Inilah alasanya mengapa “Lailatul qadr” terjadi di bulan Ramadlan, bulan dimana setiap Muslim dilatih mensucikan ruhaninya dari segala hal yang berbau profan-duniawi secara istiqamah selama satu bulan. Bagi individu yang mendapatinya, jiwa dan hatinya mendapatkan asupan “nutrisi” spritual yang luar biasa dan diikuti proses peremajaan dan pembaharuan unsur-unsur ruhani lainnya. Melalui mekanisasi seperti ini, ia akan mengalami lompatan peningkatan kualitas kemanusiaan, baik aspek moral, mental, dan emosi.
Jadi, sebagai peristiwa spritual-personal, Lailatul qadr adalah hâl (keadaan) sebagai hasil dari rangkaian ibadah dalam rentang waktu yang lama secara khusu’ dan istiqamah yang tidak selalu terjadi di malam hari. Namun demikian, waktu malam diyakini jauh lebih memungkinkan bagi Muslim untuk mengalaminya karena faktor suasana alam yang gelap, sunyi dan hening, sembari ada harapan ia terjadi di siang hari bagi umat Islam yang tidak mendapati waktu malam. Wallahu a’lam.