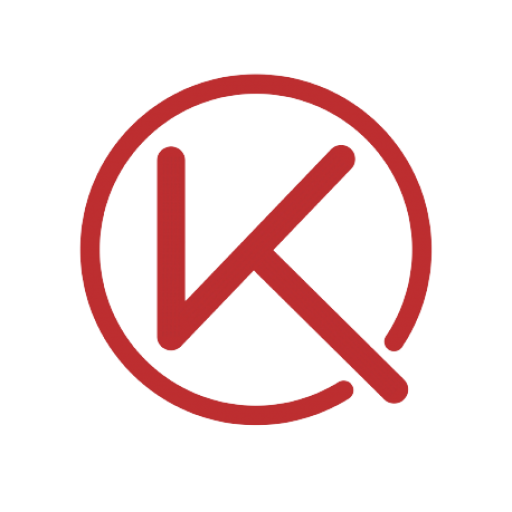kicknews.today – Bandar udara Aksu tertutup kabut tipis manakala roda pesawat Boeing 737-700 milik maskapai China Southern Airlines menyentuh ujung landasan pacu tepat pukul 10.00 waktu setempat.
Dari jendela pesawat terlihat beberapa personel militer berlari-lari kecil mengitari dua unit pesawat nirawak warna hitam mirip kalajengking raksasa.
Dibandingkan dengan Kashgar, Bandara Aksu relatif lebih kecil dan hanya melayani penerbangan domestik China saja.
Meskipun kota kecil, geliat industri di kota yang berbatasan langsung dengan Kirgistan dan Uzbekistan di sebelah barat itu lebih terlihat dibandingkan dengan kota kecil lainnya di Daerah Otonomi Xinjiang.
Pabrik tekstil, utamanya. Karena kota yang dihuni 695 ribu jiwa yang mayoritas dari kalangan etnis minoritas Muslim Uighur itu juga banyak terdapat perkebunan kapas.
Salah satu pabrik tekstil terbesar di Aksu adalah Huafu Color Co Ltd. Perusahaan yang mempekerjakan sekitar 5.000 karyawan ini termasuk salah satu perusahaan di Xinjiang yang terkena sanksi oleh Kementerian Perdagangan Amerika Serikat atas dugaan kerja paksa terhadap etnis Uighur.
Sejak sanksi tersebut diberlakukan pada Desember 2020, Huafu mengalami kerugian yang mencapai angka 400 juta yuan atau sekitar Rp895,8 miliar.
Produk utama berupa benang dan bahan tekstil lainnya untuk ekspor ke Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan Korea Selatan.
Merek-merek pakaian jadi dan perlengkapan olahraga ternama seperti Adidas, Nike, H&M, Zara, dan Uniqlo mendapatkan pasokan bahan dari Huafu.
Saat ANTARA menyambangi kompleks industri Huafu pada 20 April 2021 memang tidak banyak terlihat aktivitas para pekerja.
Di bagian pemintalan benang hanya ada beberapa orang saja. Beberapa mesin juga ada yang dikeluarkan dari ruang produksi. Bisa jadi hal itu sebagai dampak dari sanksi tersebut.
Ada sekitar enam sampai sepuluh orang pekerja yang bermain basket dan bulu tangkis di lapangan terbuka pabrik tekstil itu.
Lalu tiga pekerja lain bercengkerama di lorong mes dengan tangan membawa wadah makanan dan minuman yang tandas isinya.
Di kantin ada sekitar delapan sampai sepuluh orang yang mulai mengambil jatah makan siang dan menyantapnya di situ pula.
Semuanya warga etnis Uighur yang selama ini dikenal sebagai kelompok minoritas Muslim di China. Di antara mereka laki-laki dengan fisik sehat yang tampak menikmati santapan siang sehingga tidak peduli dengan kedatangan delegasi media asing.
“Kami tidak bisa memaksa mereka agar berpuasa atau tidak,” jawab GM Huafu Textile Co Ltd, Li Qiang, menanggapi pertanyaan para wartawan media asing yang melihat karyawan makan-makan pada tengah hari bulan Ramadhan.
Pihaknya hanya wajib memenuhi kebutuhan makan para karyawannya yang beretnis Uighur dengan menu halal atau qingzhen.
“Persoalan puasa atau aktivitas keagamaan lainnya, itu urusan mereka pribadi. Kalau mau shalat, mereka bisa pergi ke masjid,” tambah pria itu seraya menyebutkan bahwa ada tiga masjid di sekitar pabriknya.
Konsekuensi
Suasana Ramadhan tidak ada yang berbeda dengan suasana bulan lainnnya di Xinjiang, meskipun mayoritas penduduk di wilayah barat daya China itu beretnis Muslim Uighur.
Kegiatan anak-anak di sekolah juga seperti biasa. Olahraga di tempat terbuka di tengah teriknya matahari juga dilakukan para murid Sekolah Dasar Awati di Prefektur Kashgar pada 19 April 2019.
“Tidak ada yang berpuasa,” jawab Kepala SD Awati, Ayi Humae Alimu, menanggapi pertanyaan para wartawan terkait aktivitas mereka selama bulan Ramadhan ini.
Sebagian besar dari 2.727 murid SD itu tinggal di dalam asrama karena rumah mereka di desa yang relatif jauh dari sekolahan, ada yang sampai 8 kilometer.
Program wajib pendidikan dasar di Kashgar dan kota-kota lain di wilayah selatan Xinjiang berlangsung selama 15 tahun.
“Berbeda dengan di wilayah lain di China,” kata perempuan berusia 27 tahun yang sudah empat tahun menjabat Kepala SD Awati itu.
Tidak hanya puasa, pelajaran agama Islam juga tidak diajarkan kepada anak didiknya karena memang sesuai undang-undang yang berlaku di China ditegaskan bahwa remaja berusia 18 tahun ke atas baru boleh belajar agama.
Dalam undang-undang itu ditegaskan pula bahwa institusi pendidikan harus terpisahkan dari berbagai unsur agama, termasuk ruang beribadah dan segala aktivitasnya.
Berpegang undang-undang tersebut, pemerintah China tidak menganjurkan para murid sekolah menjalankan ibadah, termasuk puasa Ramadhan, di dalam lingkungan pendidikan, kecuali lembaga pendidikan Islam.
“Kalau mereka mau beribadah bisa dilakukan di rumah atau di masjid. Setiap libur Sabtu-Minggu, mereka diizinkan pulang. Di sana mereka boleh melakukan ibadah,” kata juru bicara Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang, Ilijan Anayat, Selasa (20/4).
Hal itu juga diakui oleh Tursunjan Mamat (33), warga Yiganqi, Aksu, yang mengaku tidak memberikan pengetahuan agama kepada dua anaknya sebelum berusia 18 tahun.
“Saya shalat dan mulai puasa Ramadhan sejak 2015,” ujarnya didampingi istrinya, Marbiyah Anwar yang saat itu mengenakan busana lengan pendek selutut tanpa penutup kepala.
Di depan awak media, Mamat menunjukkan musala lengkap dengan Al Quran berikut terjemahan dalam bahasa Uighur di dalam rumahnya. Sayang, dia tidak bersedia saat diminta membacanya tanpa memberikan alasan apa pun.
“Maaf, saya tidak menyediakan makanan dan minuman karena saya dan keluarga sedang berpuasa,” ucapnya memohon maklum.
Ia merasa perlu menyampaikan hal itu karena dua rumah tetangganya di Yiganqi menyuguhkan makanan dan minuman kepada 13 awak media dari Amerika Serikat, Italia, Spanyol, Tunisia, Pakistan, Jepang, dan Indonesia yang berkunjung pada sore hari itu.
“Silakan dicicipi. Saya tidak puasa karena saya memang tidak beragama,” kata Mamatjan Ahat (34) melalui bantuan seorang penerjemah bernama Hamid dari Kantor Departemen Publikasi Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang.
Pria lulusan kamp vokasi Aksu yang kini bekerja sebagai sopir truk itu mengaku kedua orang tuanya beragama Islam.
“Saya tidak. Karena saya suka minum (minuman keras) dan perokok,” ucapnya mengenai alasannya untuk menentukan hidupnya sebagai seorang ateis bersama istrinya, Sahibjamal Tohti (32), itu.
“Kedua orang tua saya tahu atas pilihan saya dan mereka juga tidak bersikap apa-apa,” tambahnya lagi.
Pilihan hidup seperti Mamatjan Ahat ini banyak dilakukan oleh generasi zaman sekarang dari kalangan etnis Uighur yang sejak lama dikenal sebagai etnis minoritas Muslim di China.
China telah memberikan kebebasan kepada warganya, apa pun latar belakang etnisnya, untuk memilih menjadi orang beragama atau ateis.
Dan, setiap pilihan itu tentu ada konsekuensinya, mengingat China merupakan negara sosialis yang menerapkan hukum secara ketat dan otoriter. Apa pun agama yang dianut warganya, ideologi Komunis tetap harus dinomorsatukan dan dijunjung tinggi.
Meskipun demikian, China tetap menyediakan fasilitas ibadah bagi warganya yang memeluk agama tertentu. Di tempat yang sudah ditentukan itulah mereka bisa melakukan berbagai macam kegiatan beribadah, termasuk shalat dan puasa bagi yang beragama Islam.
Namun jika seseorang memilih untuk beragama, maka kesempatan menjadi pegawai negeri sipil, karyawan perusahaan pelayanan publik atau BUMN, dan berkarier di struktur Partai Komunis sebagai partai penguasa tunggal di China akan hilang. Itulah konsekuensinya.
“Mereka bisa pilih. Kalau mau sembahyang atau melakukan kegiatan ibadah, jangan jadi pegawai negeri. Kalau mau jadi pegawai negeri, jangan memilih beragama,” kata Wakil Direktur Propaganda Partai Komunis China (CPC) Daerah Otonomi Xinjiang, Xu Guixiang, saat ditemui di areal Masjid Idkah, Kashgar, pada 19 April 2021. Tamat. (ant)