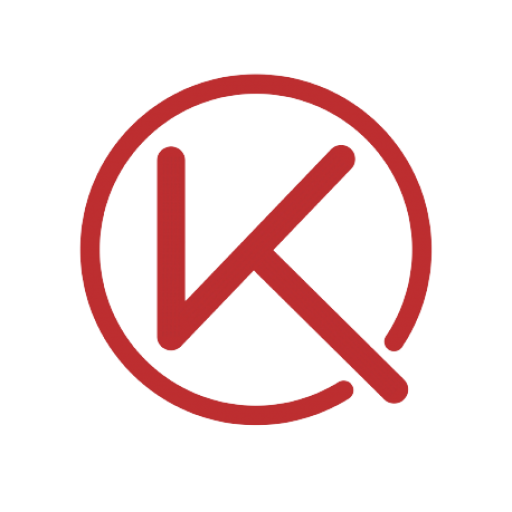kicknews.today – Orang-orang yang baru mengenal H Lalu Agus Fathurrahman boleh jadi akan sulit menebak. Dengan mengamat-amati janggutnya yang putih panjang, misalnya. Jika bukan ustadz, barangkali guru silat. Tapi ia memakai topi kodok, blue jeans, dan sandal gunung. Mana ada ustadz atau pendekar bertutup kepala yang identik dengan kesenimanan.
Keunikan Agus tak hanya di sisi penampilannya sehari-hari. Ia sosok yang memiliki bejibun keahlian. Sejumlah profesi pernah ia geluti. Mulai dari wartawan, guru, filolog, arsitek, dosen, pelukis, novelis, penyair, hingga birokrat. Ia juga dikenal sebagai sosok budayawan paling kritis.
Namun, dengan rendah hati ia mengakui tidak memiliki basis pendidikan formal untuk menguasai sederet kemampuan itu. “Saya berpura-pura menjadi penulis. Tapi, bahkan mereka yang benar-benar penulis, berhasil saya kelabui. Mereka menganggap saya seorang penulis,” kata bekas Kepala Taman Budaya dan Museum Negeri NTB ini.
Tentu saja siapa pun tak memandang sebelah mata kemampuan lelaki kelahiran Sengkol, 17 Agustus 1957 ini. Bagaimana mungkin ia berpura-pura, ketika ternyata ia telah menulis lima buah novel dan delapan buku yang digunakan sebagai referensi penting di sejumlah perguruan tinggi.
Bahkan, ucapnya lagi, Universitas Mataram (Unram), perguruan tinggi paling masyhur di NTB, juga berhasil terkecoh. Ia akhirnya ditunjuk sebagai pengajar di dua bidang ilmu sekaligus, yaitu filologi dan arsitektur.
Lalu, bagaimana caranya Agus memperoleh multi pengetahuan itu? Dengan tenang ia menjawab, “Itu gara-gara saya mencintai seorang gadis cantik.”
Jawaban yang lagi-lagi membuat penasaran. Apakah yang dia maksud istrinya yang sekarang, atau barangkali pernah punya selingkuhan atawa perempuan idaman lain? “Sudah cantik, pintar pula. Dia pun doktor. Saya berhasil menaklukkannya,” tutur penulis novel Sanggarguri, karya bernuansa sufistik yang diterbitkan Gramedia ini blak-blakan.
Nama gadis itu Filologika. Dari sinilah sumber banyak ilmu yang dimilikinya. Filogika, sebuah ilmu yang mengkaji literatur-literatur purba. Secara mandiri ia mempelajarinya. “Untuk menaklukkannya, kita mesti siap menjadi orang kuno,” ujarnya.
Filologika dari bahasa Yunani, philogia, artinya mencintai kata-kata. Di Indonesia disebut bahasa kawi. Bukan merujuk pada tempat atau daerah, tapi kawi maknanya karang-mengarang.
Teks-teks kuno bisa ditemukan di media apa saja, seperti tulang, kulit hewan, kertas, daun lontar, atau prasasti. Narasi-narasi yang mengisyaratkan adanya berbagai informasi di masa lampau. “Untuk bisa memahami teksnya, kita harus memahami aksara dan bahasanya. Bukan hanya mengartikulasikan huruf, tapi mampu membaca dengan rasa, kepekaan, dan kecerdasan bahasa,” papar Agus.
Hampir semua aksara kuno itu dikategorikan aksara sastra. Satu huruf saja bisa memiliki banyak makna. Untuk itu, seorang filolog mesti menggunakan banyak pendekatan, diantaranya semiotika dan hermeneutika.
Sejak tahun 2021 lalu, Agus juga menjadi pengajar utama di Sekolah Filologika yang diselenggarakan Museum Negeri NTB. Peminatnya beragam, mulai pelajar, dosen, penulis, hingga birokrat.
Ia telah pensiun sebagai pegawai negeri pada 2013 lalu. Tapi, minatnya pada naskah-naskah tua tak turut berhenti. Ke mana-mana ia menenteng kamera dan scanner. Jika ia temukan naskah-naskah tua koleksi pribadi, ia memohon ijin kepada pemiliknya untuk dicopy. Di laptopnya, ratusan kitab penting telah berhasil ia digitalkan.
Seperti para pendahulunya, orang-orang Sasak yang punya cara sendiri untuk menyibak tabir. Bedurus, suatu kata arkais, bermakna menemukan, dengan menggali sesuatu yang belum diketahui. Dan Agus pun terus bedurus, tak pernah berhenti mencari jawaban. (Buyung Sutan Muhlis)