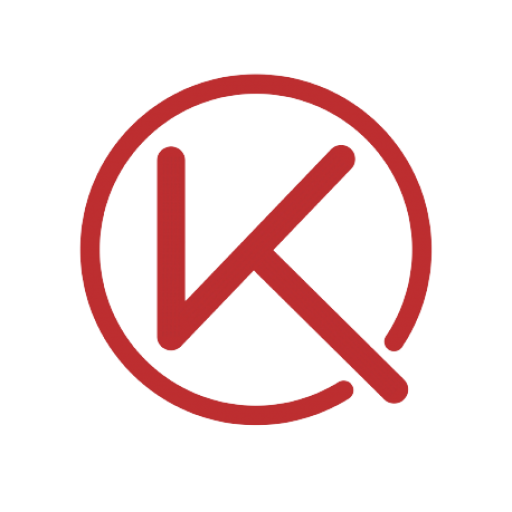Revisi UU ITE, terus menggema usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menimpali kegaduhan penerapan UU ITE, pada rapat pimpinan TNI-Polri, Senin (15/2/2021). Menurut Jokowi, hulu persoalan dari UU ITE adalah pasal-pasal karet atau yang berpotensi diterjemahkan secara multitafsir, jika revisi dilakukan, ia akan meminta DPR menghapus pasal-pasal tersebut. Pernyataan demikian, menyingkap pemikiran yang tumpul terhadap pemaknaan hukum dan penafsiran dalam hukum.
Hingar Bingar
Kegundahan Jokowi, ditindak lanjuti dengan meminta Menkumham untuk menyiapkan revisi UU ITE dan disambut meriah oleh berbagai kalangan. Mayoritas anggota DPR pun, memberikan sinyal melayani gairah Jokowi untuk kembali merombak sebuah Undang-undang.
UU ITE, pertama kali disahkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Awalnya UU ITE disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (e-commerce) serta mersepon berbagai perkembangan kejahatannya di Indonesia. Di tengah perjalanan, alih-alih memberikan rasa aman terhadap aktivitas transaksi elektronik, aparat penegak hukum justru terjebak dengan lingkaran Pasal 27 dan Pasal 28, yang terjadi terjadi kemudian gempuran kasus yang menimbulkan pro kontra terhadap pasal-pasal di UU ITE, terutama terkait dengan penggunaan media sosial yang memberikan dominasi jeratan pidana penghinaan dengan Pasal 27 ayat (3). Malahan, aktivitas pembobolan rekening, email, kontak/data pribadi dan berbagai modus “penipuan” bebas berkeliaran dan kebanyakan tidak mampu dibendung oleh aparat penegak hukum.
Mencermati perkembangan, kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Perubahan terakhir, merupakan hasil revisi dengan memerhatikan sepak terjang khususnya penerapan Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan/pencemaran nama baik melalui media elektronik, yang mempertegas penjelasan yaitu mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 27 ayat (3) pun pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak dua kali, dan hasil Judicial Review tidak menunjukkan adanya permasalahan.
Revisi kedua kalinya terus dikobarkan oleh berbagai kalangan walaupun telah mengalami revisi sebelumnya. Dorongan revisi juga dianggap sebagai reaksi dari kekecawaan penerapan hukum, namun jauh melebihi itu, revisi UU ITE seharusnya menjadi momentum untuk menata kembali cara pendang terhadap kejahatan dan sistem penghukuman.
Biang Kerok
Pasal 27 ayat (3), dianggap biang kerok kegaduhan. Nuansa kritik terhadap pelayanan ataupun kinerja pemerintah/pejabat publik dijerat pula dengan pasal ini. Di samping itu, penghinaan terhadap institusi/lembaga pun digunakan Pasal ini. Padahal, dalam perubahan sudah tertera jelas bahwa mengacu pada KUHP, yang merupakan delik untuk melindungi diri seorang (bukan institusi/lembaga), pelaku penghinaan sengaja menyerang kehormatan dengan menyebutkan identitas mengarah pada korban, sehingga memiliki nilai subyektif tergantung pada derajat kalimat penghinaan yang ditangkap, maka itu pula sebabnya menjadi delik aduan, yang tentu harus diadukan oleh seorang yang bersangkutan.
Walaupun, UU ITE telah direvisi memasukan penjelasan Pasal 27 (3), pada lingkup penerapan masih banyak dijumpai penggunaan penghinaan untuk pejabat publik/institusi dan bahkan diadukan oleh orang lain, sehingga jeratan Pasal 27 (3) belum mampu mengakhiri kegaduhan. Sisi lain, di era pemilu dan pilkada adalah ajang adu kekuatan melakukan pengaduan. Maka, tidaklah mengherankan pengaduan, proeses sampai putusan kasus penghinaan melalui media elektornik mengalami kenaikan angka yang terus melesat.
Energi Hukum
Dintinjau dari hukum pidana, rumusan perbuatan yang tercakup dalam Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan merupakan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan dilarang oleh negara yang dituliskan dalam UU ITE. Maka perbuatan yang mengarah pada unsur pasal tersebut, telah disediakan saluran mekanik “sistem peradilan pidana” (criminal justice system) yang mengolah mulai dari proses penyidikan di Kepolisian sampai dengan pelaksanaan hukum di lembaga pemasyarakatan.
Penggunaan sistem peradilan pidana, melalui jalur law enforcement (penegakan hukum) yang menitikberatkan operasionalisasi peraturan perundang-undangan, ada baiknya berirama dengan social defense (perlindungan sosial) dalam setiap reaksi terhadap perbuatan jahat. Polisi maupun Jaksa telah diberikan ruang dengan ketentuan Undang-undang untuk menggunakan kebijaksanaanya, ataupun menilai berdasar pertimbangan moral dengan batasan yang gariskan oleh undang-undang. Perubahan aturan teknis kelembagaan pun telah beranjak dari orientasi pembalasan, menuju pikiran tujuan pidana. Pada perkembangannya Kepolisian maupun Kejaksaan memiliki tekad untuk berevolusi dengan mengeluarkan Perkap dan Perja tentang Penyelesaian dengan restorative justice.
Selain itu, hakim pun diberikan kebebasan oleh Undang-undang, dengan ketentuan memutuskan dengan keyakinan berdasar dua alat bukti (pembuktian negatif). Kebebasan hakim tentu tidak memberikan makna kebebasan tanpa batas. Kebebasan hakim memberikan makna kedudukan hakim untuk menemukan hukum (rechtvinding) ataupun menafsirkan Undang-undang dengan berbagai metode berdasar prinsip dan sistem hukum (Lihat J.A Pontier, Rechtvinding (2008) dan Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (2010)).
Jika cara berhukum hanya diletakan pada norma hukum yang tertera dalam undang-undang (teks), maka persoalan pasal karet, tidak akan pernah berujung, setiap undang-undang setidak-tidaknya memiliki “pasal karet”. Sehingga membaca pasal tersebut harusnya kembali menengok dasar pemikiran pada Naskah Akademik, karena setiap pasal memiliki roh, dari ketentuan pasal yang telah dicermati dalam Naskah Akademik kemudian dapat pula dipertimbangkan dibentuk ketentuan misalnya berupa pedoman atau petunjuk teknis ataupun ketentuan pelengkap Undang-undang sebagi induknya,
Secara konsep pembentukan hukum dan politik hukum (ius constituendum), teks hukum tidaklah diharapkan berwatak kaku, “pasal karet” sejatinya adalah cara hukum mendeteksi dan memprediksi masa depan, beradaptasi dengan perkembangan, sebagai ruang penafsiran hakim serta jalur tempuh untuk menggapai keadilan. Untuk itu pula keberadaan hakim dengan jangkauan kewenangan penafsiran, ditunjuk untuk menggali jiwa hukum dan moralitas dari sebuah pasal.
UU ITE, memang sudah sepatutnya direvisi, tidak hanya menyoal “pasal karet”, namun penting memperkuat gerakan pemidanaan yang beroreintasi pada prinsip restorative justice sekaligus revaluasi dan mempertimbangkan perubahan haluan perangkat sistem peradilan pidana. Selain itu, berpijak pada pemikiran Ulrich Beck tentang masyarakat beresiko (risk society) di tengah arus modernitas yang mekonstruksi cara pikir mekanistis, maka nuansa kemampuan alamiah berhukum perlu dihadirkan kembali (reinventing) guna menemukan kesadaran hukum masyarakat.
Pada akhirnya, untuk mengimbangi berbagai usaha reformulasi ketentuan UU, ada baiknya Presiden Jokowi, DPR beserta penegak hukum kembali menyelami kalimat Bernardus Maria Taverne yang cukup populer, “berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, niscaya aku akan berantas kejahatan meski tanpa undang-undang sekalipun”. Maka, gelora revisi UU ITE, juga seharusnya dijadikan bagian untuk merefleksi akrobat penegakan hukum UU ITE.