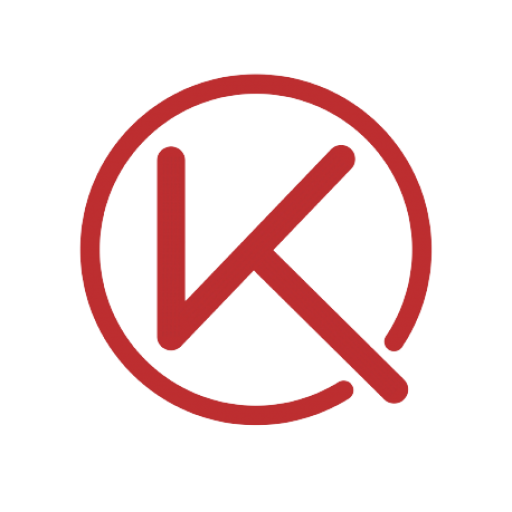kicknews.today – Langit Karbala pagi itu tidak berwarna biru. Ia seolah murung, menanti sesuatu yang tak bisa dicegah.
Pasir berdesir pelan. Debu berputar tanpa arah. Angin pun seperti menahan napas.
Hari itu, 10 Muharram 61 Hijriyah.
Di tengah padang sunyi, berdiri sebuah tenda kecil. Di dalamnya, lelaki mulia—Sayyidina Husain bin Ali, cucu manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi. Di sekelilingnya, ada anak-anaknya, saudaranya, para keponakan, sahabat-sahabat yang wajahnya bercahaya oleh iman, bukan karena pangkat atau kekuasaan.

Mereka hanya 72 orang.
Dikelilingi ribuan pasukan yang datang bukan untuk berdialog, tapi untuk memaksa. Untuk membungkam.
Semalam sebelumnya, Husain memadamkan lampu-lampu di tendanya.
Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata:
“Pergilah. Malam ini adalah malam kebebasan. Esok, hanya kematian yang menunggu.”
Tapi tak satu pun dari mereka melangkah. Tidak anak-anak, tidak wanita, tidak para pemuda.
Karena mereka tahu, esok bukan tentang hidup atau mati. Tapi tentang untuk siapa jiwa ini ditinggikan.
Pagi itu datang perlahan.
Ali al-Akbar, putra sulung Husain, meminta izin untuk maju. Wajahnya, kata orang-orang, seperti cermin wajah Rasulullah. Ia bertempur gagah, namun akhirnya gugur dengan dada penuh luka. Husain memeluk tubuhnya yang kaku, meletakkan pipinya di pipi sang anak, dan menangis dalam diam.
Lalu satu per satu, keponakan-keponakan, sahabat-sahabat, bahkan bayi kecilnya—ʿAbdullah Ar-Radhi’—semua diambil satu per satu dari pelukannya.
Husain mengangkat bayi itu tinggi-tinggi, memohon setetes air kepada pasukan di hadapannya. Tapi yang datang bukan belas kasihan—melainkan panah. Bayi itu wafat di dadanya.
Dan pada saat itu, langit seperti pecah dalam diam yang mengguncang alam.
Di akhir hari, tinggal Husain sendiri.
Lapar. Haus. Letih. Tapi tidak gentar.
Ia maju, bukan dengan pedang penuh dendam, tapi dengan jiwa yang tenang.
Ia ingin dunia tahu:
Bahwa diam di hadapan kezaliman adalah pengkhianatan.
Dan bahwa kehormatan, walau harus ditebus dengan darah, tetap lebih mulia dari sekadar hidup dalam tunduk.
Husain roboh di atas pasir Karbala.
Tubuhnya penuh luka. Kepalanya dipenggal.
Dan ketika tubuh itu tak lagi bernyawa, bumi tak bersuara.
Karbala menjadi sunyi. Tapi bukan sunyi yang biasa.
Sunyi yang mengandung ratap para malaikat, yang menyimpan isak dari langit, dan yang akan terus bergema dalam hati siapa pun yang masih peduli pada kebenaran.
Kini telah lebih dari 1.400 tahun berlalu.
Tapi sunyi itu belum pergi.
Ia hadir dalam setiap hati yang masih menangis diam-diam melihat ketidakadilan.
Ia hadir di ruang-ruang tempat suara kebenaran dipaksa tunduk.
Ia hadir di hati anak muda yang merasa sendiri saat memilih jujur, saat yang lain berpesta dengan kompromi.
Karbala tidak pernah jauh. Ia ada di setiap zaman.
Karena setiap zaman punya Yazid-nya sendiri—dan setiap hati ditanya:
Kau bersama siapa?
Jika hari ini kamu memilih diam saat kebenaran dibunuh pelan-pelan,
maka Karbala belum kamu pahami.
Jika hari ini kamu membenarkan yang salah demi kenyamanan,
maka pelajaran 10 Muharram belum menyentuh nuranimu.
Karena Husain tidak mati untuk dikenang.
Ia gugur agar kita tidak takut berdiri sendiri.
Agar ketika dunia penuh kebohongan, masih ada orang yang bersedia berkata: cukup.
اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ، وَلَوْ كَانَ الْجَمِيعُ صَامِتِينَ
Ya Allah, jadikan kami bagian dari para penolong Husain, meski seluruh dunia memilih diam. (red.)