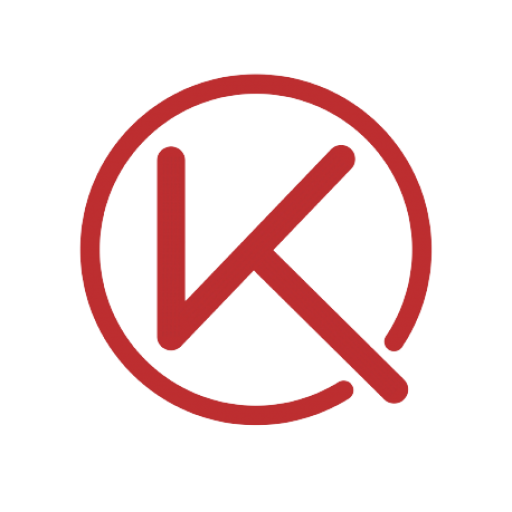Oleh: Mavi Adiek Garlosa
Di balik tembok tinggi dan baliho besar bertuliskan “Kampus Unggul dan Bermartabat,” Universitas Mataram kini sedang berdarah secara perlahan. Luka itu tidak tampak di permukaan, tapi terasa di setiap sudut ruang akademik yang mulai kehilangan rohnya. Luka itu bukan karena kekurangan dana penelitian, bukan karena minimnya publikasi internasional, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih busuk, politik kampus yang kehilangan nurani. Di tengah jargon kemajuan dan seremonial prestasi, ada kehampaan moral yang tak lagi bisa disembunyikan. Di balik senyum para pejabat akademik dan kata-kata indah tentang integritas, terselip kepentingan yang berlapis: siapa yang didukung, siapa yang dilindungi, dan siapa yang harus disingkirkan.

Pemilihan Rektor (Pilrek) yang seharusnya menjadi ajang gagasan, integritas, dan visi akademik kini menjelma menjadi arena jegal-menjegal yang memalukan. Nilai keilmuan dikorbankan di altar kepentingan pribadi dan kelompok. Calon-calon yang seharusnya berbicara tentang masa depan universitas justru sibuk membangun jaringan dan menebar pengaruh. Para pendukungnya bertarung bukan dengan ide, tetapi dengan strategi kotor yang menodai kehormatan akademik. Maka Pilrek bukan lagi pesta demokrasi kampus, melainkan cermin retak dari wajah universitas yang kehilangan jiwa, tempat di mana kuasa menjadi tujuan, dan keilmuan hanya dijadikan hiasan.
Ketika “Akademia” Berubah Menjadi “Arena”
Tak ada yang lebih menyedihkan daripada melihat para intelektual terpelajar berseteru layaknya politisi jalanan. Saling sikut, saling sabotase, saling hitung siapa yang bisa dikendalikan, bukan siapa yang pantas. Di setiap fakultas, intrik menjalar bagai kabut yang tak tampak namun mencekik. Yang berani bicara kejujuran dianggap pemberontak, yang diam demi aman dianggap bijak. Padahal diam di tengah kebusukan bukanlah kebijaksanaan, melainkan pengkhianatan terhadap nurani. Kampus yang semestinya menjadi ruang bagi akal sehat kini justru berubah menjadi medan politik yang mengajarkan kelicikan dengan wajah akademik.
Beberapa dosen muda kini hidup dalam ruang sunyi yang penuh tekanan. Di balik tumpukan jurnal dan wajah formalitas rapat, mereka menyembunyikan kegelisahan yang tak tertulis. Suara hati mereka bergetar di antara bisik-bisik “Jangan terlalu vokal, nanti sulit naik pangkat,” atau “Jangan ikut arus lain, nanti dianggap melawan pimpinan.” Mereka dilema antara memilih setia pada nurani atau tunduk pada sistem yang menindas. Ironisnya, kampus yang setiap hari mengajarkan keberanian justru menakuti keberanian itu sendiri. Di balik senyum sopan dan jargon etika akademik, tersimpan ketakutan yang mengakar, takut kehilangan jabatan, takut tak direkomendasikan, takut menjadi nama yang dicoret dari daftar “yang bisa dipercaya.”
Maka kampus pun perlahan berubah menjadi panggung sandiwara. Semua orang tersenyum, tetapi tak ada yang benar-benar gembira. Dosen muda yang seharusnya menjadi tumpuan masa depan akademik, justru tumbuh dalam budaya ketakutan. Mereka tahu bahwa di universitas ini, kebenaran tidak selalu membawa keselamatan. Dan di situlah tragedi moral itu lahir, ketika kejujuran dianggap ancaman, ketika integritas diperlakukan sebagai kesalahan, ketika kepatuhan lebih dihargai daripada keberanian. Universitas yang dulu dibangun atas nama ilmu kini justru memuliakan kepatuhan. Sementara di luar ruang rapat, mahasiswa hanya bisa menatap getir: bagaimana mungkin mereka yang mengajarkan “berpikir kritis” justru memilih diam saat moral kampus dipermainkan?
Sanksi Etik dan Keadilan yang Timpang
Beberapa fakultas kini sedang menjadi sorotan karena sanksi etik terhadap sejumlah dosen dan pejabatnya. Ironisnya, sanksi yang semestinya lahir dari niat moral justru tampak seperti alat politik yang dibungkus etika. Di ruang-ruang rapat etik, keadilan sering kali kehilangan arah; bukan kebenaran yang diadili, melainkan siapa yang berani berbeda. Ketika satu pihak dijatuhi sanksi karena melanggar norma, pihak lain yang melakukan kesalahan serupa justru dibiarkan melenggang karena “orangnya siapa”. Di sinilah moralitas akademik runtuh: bukan pelanggaran yang menentukan hukuman, tetapi kedekatan yang mengatur nasib. Kampus yang seharusnya menjadi tempat paling jujur di dunia ilmu, kini justru belajar memainkan standar ganda dengan elegannya menghukum yang lemah, melindungi yang berkuasa.
Sanksi etik seharusnya menjadi cermin untuk membersihkan lembaga dari penyimpangan moral, bukan pedang yang digunakan untuk membungkam suara yang tak sejalan. Namun kini, etik berubah menjadi instrumen represif, bukan reflektif. Ia kehilangan ruh keadilannya, menjadi sekadar prosedur formal yang digunakan untuk menekan, menakut-nakuti, dan menyingkirkan yang tidak tunduk. Maka jangan heran jika integritas kampus perlahan mati bukan karena kejahatan besar, melainkan karena kebisuan yang dipelihara. Di balik rapat etik yang tampak berwibawa, tersembunyi kebenaran yang terkubur pelan-pelan, bersama nurani yang dulu seharusnya dijaga.
Kampus yang Tak Lagi Merdeka
Universitas seharusnya menjadi ruang bebas untuk berpikir, bersuara, dan berdebat. Tapi ketika tekanan datang dari atas, ketika pilihan politik dosen diawasi, ketika suara nurani dipaksa diam, kampus bukan lagi universitas, melainkan kantor birokrasi yang berlabel akademik.
Kita sedang menyaksikan erosi perlahan dari academic freedom. Dosen-dosen yang jujur kini dianggap ancaman. Yang berani bersuara dilabeli pembangkang. Yang netral dianggap tidak berpihak. Lalu di mana letak kemerdekaan berpikir yang selama ini dibanggakan?
Ketika fakultas-fakultas menjadi medan politik, mahasiswa pun menjadi korban pasif. Mereka belajar dari contoh buruk, bahwa untuk berkuasa, cukup pandai bersiasat, bukan bermoral. Bahwa untuk menjadi rektor, cukup tahu siapa yang harus dijilat, bukan apa yang harus diperjuangkan. Miris bukan? tapi begitulah faktanya, kenyataan pahit yang terus menggerus nilai moral dan tata kelola kampus, dan pada akhirnya kampus bukan lagi tempat yang nyaman untuk berproses dan berpikir secara merdaka, melainkan hanya tempat kepentingan politik.
Ketika Rektor Dipilih Bukan Karena Layak, Tapi Karena Taktik
Sungguh menyakitkan melihat bahwa jabatan tertinggi di universitas kini tidak lagi ditentukan oleh karya dan pengabdian, melainkan oleh jaringan dan intrik. Di balik senyum formal dan pidato akademik yang berisi kata-kata luhur, tersimpan permainan kuasa yang dingin dan licik. Orang yang berani berbeda dianggap pengganggu status quo; yang berpikir kritis dicap pembuat onar; dan yang jujur sering kali terpaksa tersingkir dari lingkaran kekuasaan. Di kampus yang semestinya menjadi taman kejujuran intelektual, kini tumbuh subur politik pencitraan dan kepura-puraan.
Sementara itu, calon-calon yang benar-benar memiliki visi akademik tersingkir perlahan oleh politik kepentingan. Rapat-rapat senat bukan lagi ruang intelektual yang menimbang ide, tapi “pasar gelap” yang sibuk menghitung siapa mendukung siapa. Suara hati dikalahkan oleh suara mayoritas yang sudah diatur sejak awal. Keputusan-keputusan penting tentang masa depan universitas berubah menjadi komoditas, diperjualbelikan lewat bisik-bisik dan janji jabatan. Maka yang lahir bukanlah pemimpin yang memajukan ilmu, melainkan tokoh kompromi yang aman bagi semua pihak, kecuali bagi kebenaran itu sendiri.
Padahal rektor bukan sekedar pejabat administratif. Ia adalah wajah moral, intelektual, dan spiritual kampus, simbol tertinggi dari marwah keilmuan. Ketika kursi rektor dijadikan hasil tawar-menawar, maka yang duduk di sana bukan lagi seorang pemimpin, melainkan simbol dari kekosongan nilai. Dari sanalah lahir sebuah tragedi: universitas kehilangan arah bukan karena kekurangan orang pintar, tetapi karena kekurangan orang jujur. Ilmu tetap diajarkan, akan tetapi, nurani perlahan dikubur di bawah meja rapat. Dan kampus yang seharusnya menjadi rumah kebijaksanaan, kini terasa seperti panggung politik murahan yang hanya tersisa tepuk tangan tanpa makna.
Luka Moral yang Tak Tersembuhkan
Apa yang terjadi hari ini di Universitas Mataram bukan sekadar konflik elit kampus. Ini adalah gejala penyakit moral yang menggerogoti fondasi akademik. Bagaimana mahasiswa bisa belajar kejujuran jika dosennya dipaksa memilih karena tekanan? Bagaimana bisa menanamkan nilai integritas, jika yang menjabat justru mereka yang menang lewat intrik?
Universitas adalah tempat menanam akal sehat, tapi kini yang tumbuh justru akal licik. Kita sedang mencetak generasi yang cerdas tetapi tidak jujur, berprestasi tetapi tak berjiwa. Jika ini dibiarkan, jangan heran bila suatu hari nanti gelar akademik hanyalah simbol tanpa makna, seperti toga tanpa isi kepala.
Akan tetapi Masih ada waktu untuk memperbaiki. Tapi itu hanya bisa terjadi jika ada keberanian, keberanian dari para dosen muda untuk bersuara, keberanian senat untuk berkata “tidak” pada intervensi, dan keberanian civitas akademika untuk menolak permainan politik. Universitas Mataram bukan milik satu kelompok, bukan milik birokrat, apalagi milik jaringan politik mana pun. Kampus ini adalah rumah bagi ilmu dan kejujuran. Dan rumah ini sedang terbakar perlahan, jika tidak segera dipadamkan, abu yang tersisa hanyalah reputasi yang busuk.
Suatu hari nanti, sejarah akan mencatat, bukan siapa yang menang dalam Pilrek Unram 2026, tapi siapa yang berani melawan ketidakadilan dalam prosesnya. Dan ketika itu terjadi, mungkin kita akan menatap kembali masa ini dengan getir, sembari berkata: “Di universitas yang dulu menjunjung tinggi ilmu, kami pernah menyaksikan bagaimana moral kalah oleh siasat.” (*)
Baca juga: Masyarakat Adat Sasak minta Pemilihan Rektor Unram kembali ke jalan yang lurus
Baca juga: Setelah digugat ke PTUN, Unram akui kesalahan, SK Etik Dr. Ansar dicabut
Baca juga: Prof. Hamsu siap ikuti proses hukum, peluang maju sebagai Rektor Unram masih terbuka