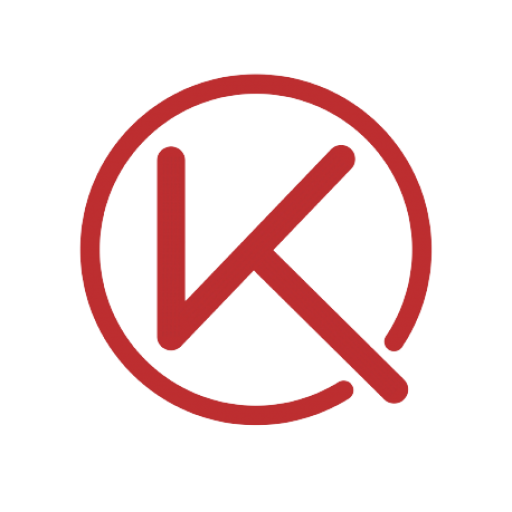Oleh: Andi Fardian, M.A
Dua pemuda yang satu provinsi asal dengan saya datang ke Jogja. Tujuan mereka ke Jogja adalah untuk mencari pekerjaan. Baginya, di daerah asalnya sana sudah tidak ada lowongan pekerjaan yang layak bagi mereka. Mereka berpikir bahwa hijrah ke Jogja adalah cara terbaik untuk mengubah nasib dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Mereka juga berpikir bahwa ijazah yang didapatkan dari perguruan tinggi tidak boleh mubazir. Masak kuliah yang menghabiskan uang banyak itu tidak dapat dipakai untuk mencari pekerjaan.

Masalahnya memang begitu. Mencari pekerjaan saat ini tidaklah mudah. Dari dulu, sih, sebenarnya. Wisuda cepat tidak menjamin seorang sarjana langsung mendapatkan pekerjaan. Apalagi wisuda telat, ya. Ada beberapa mahasiswa yang berpikir bahwa begitu lulus, langsung mendapatkan pekerjaan. Tapi pada kenyataannya, hampir selalu mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan. Mereka yang IPK tinggi pun tidak ada jaminan langsung mendapatkan pekerjaan. Apalagi yang IPK rendah, ya. Tapi seringkali terjadi mereka yang IPK rendah dan prestasi saat kuliah biasa-biasa justru lebih dulu mendapatkan pekerjaan. Artinya, menjadi mahasiswa berprestasi saat kuliah, tidak menjamin ia bisa survive dalam menghadapi kenyataan hidup.
Kedua pemuda tersebut sebelum ke Jogja menanyakan kepada kami tentang bagaimana prospek lapangan pekerjaan di Jogja. Kalau bicara lapangan pekerjaan di Jogja itu banyak sekali. Anda mau parttime, silakan. Mau fulltime juga bisa. Banyak lapangan pekerjaannya. Tapi satu hal yang harus diingat bahwa buang jauh-jauh mental gengsi dan instan.
Setelah sampai di Jogja, kedua pemuda tersebut langsung tancap gas memasukkan lamaran di berbagai tempat. Mereka melamar untuk posisi yang sesuai dengan kompetensi dan ijazah mereka. Masuk minggu kedua di Jogja, mereka sudah was-was, kok, tidak ada panggilan dari tempat mereka melamar. Tidak ada satupun panggilan lebih lanjut. Masuk minggu ketiga, mereka sudah mulai gusar. Masalahnya adalah biaya makan-minum dan kos hanya mengandalkan dari kiriman orangtua dan keluarga dari kampung.
Ketika sudah satu bulan di Jogja, mereka mulai mengeluh. Mereka merasa tidak ada kepastian. Kami tahu, dalam hati mereka, ada perasaan sedikit menyalahkan kami. Karena sebulan sebelum datang ke Jogja, ketika ditanya, ada lowongan pekerjaan, ya, kami jawab ada dan banyak. Ya, memang banyak. Akhirnya, mereka hanya bertahan di Jogja selama sebulan dan balik ke daerah asalnya, NTB.
Apa pelajaran yang ditarik dari cerita di atas? Pertama, mencari pekerjaan tidaklah mudah. Kompetisi dalam dunia kerja sangatlah ketat. Satu-satunya cara agar bisa lolos dalam persaingan tersebut adalah terus meningkatkan kualitas diri dan pengalaman. Dua pemuda pada cerita di atas adalah fresh graduate. Ketika kamu melamar pekerjaan, si pemberi pekerjaan tidak akan pernah bertanya seberapa tinggi IPK kamu, tapi yang mereka tanyakan adalah kamu bisa apa dan kualitas diri apa yang bisa kamu kontribusikan untuk mengembangkan instansi atau perusahaan tersebut. Sehingga, cara terbaik sebelum melamar pekerjaan adalah mengasah kemampuan diri. Jangan mengandalkan IPK yang tinggi atau wisuda cepat. Tidak akan terlalu berguna predikat itu.
Kedua, sikap maunya serba instan. Kedua pemuda tersebut melamar untuk posisi yang sesuai dengan ijazah mereka. Masalahnya adalah mereka fresh graduate. Orang tentu melihat curriculum vitae (CV). Jelas, pengalaman kerja belum ada. Kemungkinan besar itu yang membuat perusahaan tidak menerima lamarannya. Tidak qualified, bahasa Ranggo-nya. Tidak dipanggil berarti tidak diterima.
Ketiga, tidak bersabar. Mencari pekerjaan butuh kesabaran yang tinggi dan sikap tidak pantang menyerah. Baru tidak dipanggil sebulan saja, sudah menyerah. Wah, cemen itu. Seharusnya mereka bersabar. Semua tidak ada yang instan.
Keempat, mental gengsi. Saya tahu betul mental gengsi orang di daerah asal saya. Tapi tidak semua orangya. Mereka lebih baik menganggur daripada melakukan pekerjaan yang mereka anggap menurunkan harga diri mereka. Mereka hanya mau langsung bekerja di posisi yang mereka inginkan dan mendapatkan gaji yangtinggi. Wah, rumit juga kalau begitu. Semua ada prosesnya, coy.
Selama dua pemuda tersebut ada di Jogja, mereka hanya melamar pada posisi yang sesuai dengan ijazah mereka yang gajinya tinggi. Tapi mereka tidak mau mengambil kerjaan parttime, seperti menjadi tim marketing atau tukang cuci piring. Malu kalau melakoni pekerjaan seperti itu. Untuk apa jauh-jauh ke Jogja, kalau hanya bekerja serendah itu.
Kalau saya ada di posisi mereka, sambil menunggu panggilan dari tempat-tempat yang sudah dimasukkan lamaran, saya akan melakoni pekerjaan sebagai pencuci piring, tukang ojek, atau tim marketing. Pekerjaan-pekerjaan itu halal dan saya bisa mendapatkan uang.
Tapi memang mental gengsi dan instan dari sebagian orang di provinsi asal saya sudah mendarah daging. Mereka lebih memilih menjadi pengangguran daripada mengambil pekerjaan-pekerjaan parttime. Padahal, pekerjaan parttime bisa menjadi batu loncatan untuk menambah jam terbang pengalaman.
Pekerjaan di Jogja itu banyak, tapi kuncinya harus kuat tahan banting. Jangan langsung maunya instan dan gaji tinggi. Tidak bisa seperti itu langsung. Kami sejak semester 2 kuliah sudah bekerja parttime menjadi pelayan di warung lesehan sekaligus mencuci piring. Jadi tukang ojek pun sudah pernah. Apapun kami lakoni ketika awal berhijrah. Kalau bermental gengsi dan instan, ya, tidak bisa makan. Untuk gaji pun, kami pernah digaji 10 ribu rupiah per hari. Apakah kami merasa harga diri kami rendah? Tidak sama sekali. Justru yang membuat harga diri kami rendah adalah menjadi pengangguran dan tidak dapat menggunakan ijazah untuk bekerja.
Saya akhirnya berpikir bahwa bisa jadi salah satu faktor yang membuat angka pengangguran di NTB cukup tinggi adalah karena mental gengsi dan maunya instan saja dalam mencari pekerjaan. Mereka dan kita ini hanya maunya langsung mendapatkan pekerjaan yang mapan dan digaji tinggi.
Boleh jadi di NTB itu bukannya tidak ada lapangan pekerjaan, tapi pekerjaan-pekerjaan yang ada dianggap bisa bikin harga diri jatuh. Tapi, omong-omong harga diri tidak bisa memberi makan ‘kan?
O iya, orang NTB yang saya maksud dalam tulisan ini tentu saja tidak semuanya, tapi sebagiannya.*