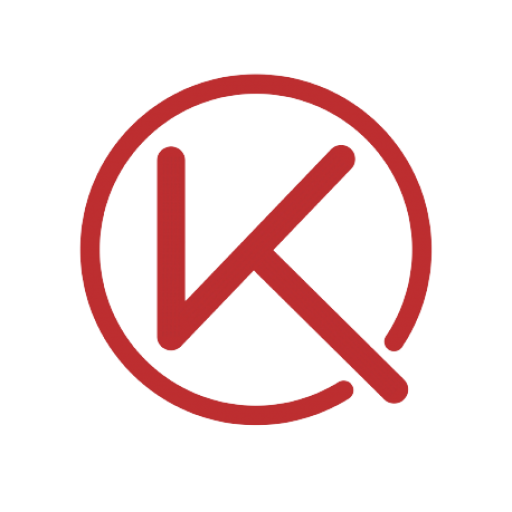Oleh: Andi Fardian, M.A
Jumlah universitas di China hanya 2.600, dengan populasi penduduk sebanyak 1,4 miliar. Tapi kualitas produk dan lulusannya jelas. Very globally competitive. Sedangkan jumlah kampus di Indonesia sebanyak 4.523, dengan populasi penduduk hanya 280 juta. Tapi kualitas, ya … silakan Anda isi sendiri.

30 universitas terbaik di Asia versi QS AUR 2024 didominasi oleh kampus-kampus di China, Korea Selatan, dan Jepang. Lantas, UI, UGM, IPB, dan ITB masuk di mana? Tidak masuk di daftar ini. Fenomena ini saya sebut sebagai ‘jago kandang’. Ibaratnya klub sepakbola; jagonya kalau main di home, tapi kalah di away. Maafkan jika saya dinilai durhaka pada almamater. Tapi saya harus kritis. Artinya, ada banyak hal yang perlu diperbaiki dari kampus-kampus kita secara khusus, dan pendidikan tinggi kita secara umum. Mari kita tinggalkan slogan-slogan formalitas itu. Mulailah fokus pada peningkatan kualitas dengan kerja nyata. Kerja nyata dalam arti yang sebenar-benarnya.
Tidak usah jauh-jauh. Sampai sekarang belum bisa masuk di nalar saya, di kampus-kampus tertentu, dalam satu kelas ada 40–70 mahasiswa yang diampu oleh 1 atau 2 dosen. Menurut Anda, berkualitas dan proporsionalkah materi perkuliahan jika sebanyak itu mahasiswanya? Alih-alih terbentuk suasana akademik, yang ada justru vibes pasar. Yang mendengar suara dosen hanya yang duduk di depan. Yang belakang, ya, wassalam. Lalu, kualitas mahasiswa seperti apa yang diharapkan kalau model kuliahnya seperti itu? Karena itu jangan heran ketika banyak mahasiswa yang tidak nyambung kalau berdiskusi.
Apa itu yang namanya kehadiran kampus mencerdaskan bangsa? Belum tentu. Coba Anda jawab, bagaimana logisnya kampus mencerdaskan bangsa kalau yang mendengar penjelasan dosen hanya segelintir mahasiswa yang duduk paling depan? Apa ini bukan omong kosong?
Tapi memang, berbisnis di dunia pendidikan tinggi itu sangat menguntungkan dan menggiurkan. Bisa mematok uang pembangunan, uang pengembangan, uang gedung, uang kursi, dan UKT sebanyak mungkin. Terkait uang gedung ini, ibaratnya Anda beli ikan, tapi Anda juga harus membayar biaya timbangan, biaya plastik, dan sebagainya. Situasi ini, dalam kajian sosiologi, disebut involusi: kuantitas meningkat, tapi kualitas menurun.
Karena itu, banyak orang tertarik bikin kampus. Makin menguntungkan lagi dengan bikin kebijakan TOEFL dan tes serupa lainnya. Semua bisa dipakai sebagai alat untuk menarik uang dari mahasiswa.
Jiwa kapitalis saya meronta-ronta untuk bikin sekolah tinggi atau kampus kecil-kecilan. Ya, karena untung besar itu. Berbekal ruko dua lantai pun bisa jadi kampus. Urusan izin gampang, apalagi kalau … Nanti bisa pakai branding dan marketing ‘mengakar secara lokal, kompetitif secara global’, saya yakin laku ini barang. Apalagi ditambah dengan strategi pemasaran “Gratis biaya dua semester dan laptop jika daftar ulang lebih awal”. Tambah laris lagi kalau pakai embel-embel beasiswa. Jika dulu beasiswa itu sakral, tidak semua orang bisa mendapatkannya. Sekarang, sudah jadi alat strategi pemasaran demi menarik calon mahasiswa agar daftar ke kampus-kampus tertentu. Beasiswa mengalami penyempitan makna; diobral dan dijadikan alat jualan.
Hari-hari ini term atau frasa “berdaya saing internasional” adalah yang paling laris dan disukai orang. Orang-orang terhipnotis dengan kata “meng-internasional”. Padahal itu hanya kata dan benda mati. Berdaya saing internasional, tapi perkuliahan masih menggunakan bahasa Indonesia, ya, susah. Coba jelaskan, bagaimana alur berpikirnya perihal term “meng-internasional” itu?
Hanya saja, apa tega saya mengeksploitasi jiwa kapitalis saya. Pemerintah Indonesia seharusnya rigid dengan permohonan membentuk kampus baru. Ayolah, mau dibawa ke mana kualitas generasi masa depan bangsa? (*)