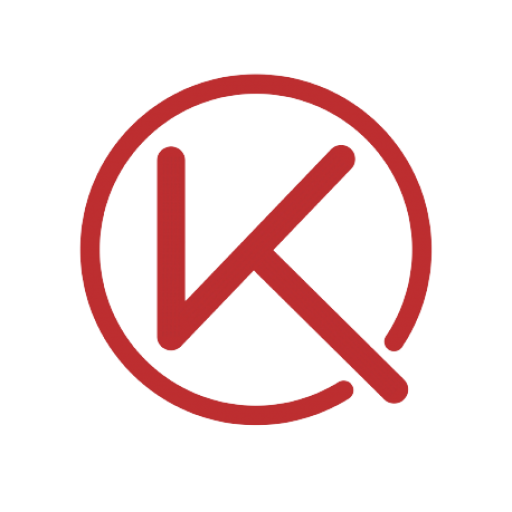Oleh: Junardi, S.Pt., M.Sc
Ada momen-momen yang tidak perlu dijelaskan dengan data. Ia cukup dirasakan. Dari suasana pasar yang mendadak lebih ramai, wajah-wajah tamu dari luar daerah yang tersenyum di warung kecil, hingga kesibukan warga yang seolah sedang menyambut sanak saudara yang pulang kampung. Itulah yang terjadi di NTB saat Fornas kita ini digelar.

Bukan sekadar singkatan dari Festival Olahraga Rekreasi Nasional, Fornas Kita adalah nama yang menempel akrab di bibir masyarakat NTB beberapa pekan terakhir. Di jalan-jalan, di warung kopi, di status WhatsApp emak-emak posyandu, bahkan di pembicaraan anak-anak yang penasaran kenapa tetangga mereka sekarang jadi panitia, jadi penari, atau jadi petugas venue. Fornas Kita adalah perayaan bersama yang tidak eksklusif, ia milik semua yang terlibat.
Sejak kontingen dari 38 provinsi mulai berdatangan, NTB terasa seperti rumah besar yang mendadak penuh tamu. Tapi ini bukan tamu asing. Ini tamu yang disambut dengan tangan terbuka dan wajah berseri. Dari bandara hingga pelabuhan, dari kelurahan hingga pusat kota, semua bersiap. Bukan untuk sekadar menyelenggarakan event, tapi untuk menunjukkan siapa kita: masyarakat yang ramah, hangat, dan bangga akan daerahnya.
Saya bertemu Ibu Janah, penjual cilok kuah dari Belencong, Kecamatan Selaparang. Biasanya ia berkeliling. Tapi selama Fornas, ia menetap di sekitar venue utama karena dagangannya ramai.
“Biasa saya pulang sore, sekarang jam dua sudah habis. Banyak yang dari luar daerah beli. Saya senang, walau saya cuma jual cilok, tapi saya merasa bagian dari acara besar ini,” katanya, suaranya pelan, terlihat sesekali menyeka matanya yang berkaca.
Dalam senyum Ibu Janah, ada semangat yang tidak bisa dibeli dengan APBD. Ada rasa ikut memiliki, rasa dihargai, rasa punya andil meski tanpa jabatan atau nama di spanduk.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, tahu betul nilai itu. Dalam pembukaan, ia berkata:
“Ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang semua senang.”
Kalimat itu bukan sekadar seremoni, tapi diterjemahkan ke dalam cara kerja: 90 persen vendor berasal dari NTB, pelaku seni lokal diberi ruang besar, UMKM didorong naik kelas, dan relawan muda diberi tanggung jawab nyata. Inilah semangat Fornas Kita bersama yang bukan cuma sekedar ajang kompetisi elite, tapi panggung rakyat yang membumi.
Saya melihat anak-anak muda yang biasanya nongkrong tanpa arah, kini mengenakan ID card dan memandu kontingen luar dengan bahasa Indonesia yang percaya diri. Saya melihat ibu-ibu yang biasanya senam di gang perumahan, kini tampil di hadapan ratusan pasang mata. Saya melihat pemuda-pemuda kampung yang biasanya malu bicara, kini berdiri tegap di panggung pertunjukan budaya.
Dan NTB pun berubah. Bukan karena panggung megah atau lighting video mapping canggih, tapi karena kepercayaan diri kolektif yang tumbuh dari partisipasi bersama. Kita merasa mampu, dan kita membuktikannya tanpa harus ribut soal pengakuan. Karena Fornas Kita ini memang bukan sekadar acara, ia adalah rasa.
Pembukaan Fornas Kita ini memang telah usai. Tapi gelombang semangatnya belum berhenti. Lomba masih berjalan, pengunjung masih berdatangan, dan cerita-cerita kecil terus tumbuh di warung-warung dan halaman rumah. Seperti Lebaran, ketika hari raya selesai tapi suasana hangatnya masih tinggal berhari-hari setelahnya.
Mungkin ini bukan peristiwa yang akan masuk catatan sejarah nasional. Tapi di hati warga NTB, Fornas Kita ini akan selalu dikenang sebagai momen ketika kita semua merasa menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Tanpa harus naik podium, tanpa harus diberi medali.
Dan untuk itu, kita semua sudah menang. (*)