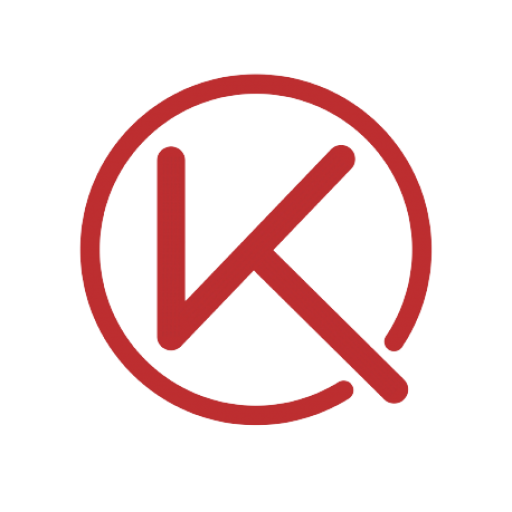kicknews.today – Setiap tahun orang-orang menumpahkan air mata di pesisir itu. Ketika puluhan perahu bolak-balik dari pantai menuju kapal yang melepas jangkar setengah mil dari dermaga.
Lebih dari separuh warga Pulau Lombok memadati sepanjang pantai Ampenan di hari itu. Semua melambaikan tangan, membiarkan air mata yang tidak dapat terbendung lagi. Lambaian tak berhenti sebelum perahu-perahu terakhir menghilang dari pandangan.
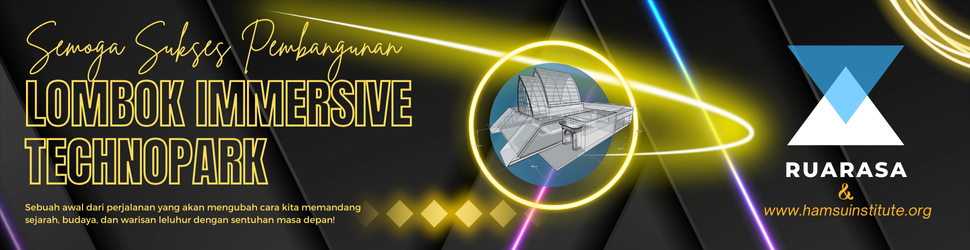
Momen mengharukan itu tak pernah dilupakan Abah Hasan, seorang guru matematika. Ia sudah menginjak remaja di tahun-tahun terakhir Pelabuhan Ampenan beroperasi di pertengahan 1970an.
“Orang-orang menangis melepas para jamaah calon haji. Tak hanya keluarga jamaah, tapi hampir semua yang ikut mengantar kepergian mereka yang dibawa menggunakan perahu. Di tengah laut, sebuah kapal besar menunggu,” tutur warga Sukaraja, Ampenan Tengah ini.
Sejak beberapa minggu sebelumnya, Ampenan tak pernah sepi. Orang-orang berdatangan dari berbagai penjuru Lombok. Mereka mendirikan kemah-kemah. Membawa perbekalan yang cukup hingga hari pemberangkatan. Diperkirakan jumlahnya lebih dari 100 ribu orang, bahkan melebihi jumlah penduduk kota pelabuhan itu.
“Seorang calon haji yang ada di satu desa di Lombok diantar oleh orang sekampung. Bagaimana Ampenan tidak ramai, mulai dari sekitar jembatan Ampenan hingga pesisir pantai dipadati manusia,” ujarnya.

Hari-hari di Ampenan bagaikan lautan manusia itu sudah berlangsung dua puluhan tahun sebelum itu. Suasana pemberangkatan jamaah calon haji asal Lombok di tahun 1956 digambarkan H Bochri Rahman, mantan wartawan RRI Mataram.
Ia bersama puluhan warga Jembatan Kembar, Lembar, yang membawa satu cikar (dokar tanpa atap) perbekalan, ikut mengantar seorang jamaah dari kampung mereka. Rombongannya mendirikan tenda di halaman rumah H Yusuf, Ketua Penyelenggara Haji Indonesia (PHI) Lombok, di Lingkungan Gang Buntu, Ampenan.
“Kota tua Ampenan ramai sepanjang malam. Jarang orang tidur karena perasaan senang bisa datang ke Ampenan dan menjemput pahala. Lantunan berzanji terdengar di mana-mana, mewarnai malam-malam pengantaran jamaah calon haji. Terasa seperti berlangsungnya sebuah pesta. Di hari pemberangkatan Pantai Ampenan penuh sesak dengan para pengantar. Terik panas tidak terasa, karena bahagia bisa mengantar jamaah calon haji,” ungkap Bochri Rahman.
Sebelum berangkat para pengantar berebutan mencium tangan masing-masing jamaah. Dari sinilah keharuan mulai menguasai perasaan. Mereka seperti melepas orang-orang yang berangkat ke medan perang. Sulit, berbahaya, dan rumitnya perjalanan menunaikan ibadah haji, membuat keluarga dan seluruh pengantar pasrah. Perjalanan haji yang menempuh risiko besar, sehingga orang-orang sadar bahwa besar kemungkinan mereka tak kembali. Antara hidup dan mati.
“Orang-orang berdoa, jika pun ada jamaah yang menemui ajal, semoga mereka mati syahid di tanah suci, bukan di laut,” kata Abah Hasan.
Keharuan tak hanya mewarnai hari pemberangkatan. Setelah para jamaah berada di samudera lepas, RRI secara rutin menyiarkan berita keberangkatan calon haji.
“Acara favorit saat itu adalah berita haji dan All England,” ucapnya.Dari Stasiun RRI Jakarta, Hasan Asy`ari Oramahi, membacakan berita tentang perjalanan jamaah yang masih berada di atas kapal.

“Saudara-saudara, badai besar sedang dihadapi beberapa kapal pembawa jamaah calon haji Indonesia yang baru memasuki Laut Merah. Mari kita memanjatkan doa agar para jamaah diberikan ketabahan dan keselamatan,” ucap Abah Hasan, mengutip berita yang disampaikan Hasan Asy`ari Oramahi.Kabar terombang-ambingnya kapal-kapal jamaah diterjang badai di tengah laut lepas itu, memicu keresahan kolektif.
Orang-orang kembali berurai air mata. Doa-doa dipanjatkan. Ampenan dicekam kecemasan. Tak sedikit yang meraung-raung menangis, membayangkan kapal para jamaah tak ubahnya ubal-ubal (pelampung pancing) yang timbul-tenggelam dihempas gelombang.
“Para jamaah pasti akan menghadapi badai laut tersebut. Jika tak ditemukan waktu berangkat, nanti pasti berlangsung di saat kepulangan. Warga terus memonitor perkembangan perjalanan laut jamaah,” ujar Abah Hasan.
RRI juga menyiarkan para jamaah yang meninggal dunia di atas kapal. Jenazah mereka dikuburkan di tengah samudera. Untuk ke sekian kalinya tangis pecah di setiap penjuru.
“Tapi setelah sampai di Pelabuhan Jeddah dan jamaah mulai berangkat menuju Mekah, tidak ada berita selama hampir dua bulan,” lanjutnya.
Sastrawan Melayu Abdullah bin Abdulkadir Munsyi mengisahkan badai laut yang dihadapinya ketika menunaikan ibadah haji di tahun 1854.
“Tiada dapat hendak dikabarkan bagaimana kesusahannya dan bagaimana besar gelombangnya, melainkan Allah yang amat mengetahuinya. Rasanya hendak masuk ke dalam perut ibu kembali, gelombang dari kiri lepas ke kanan dan yang di kanan lepas ke kiri,” tulisnya dalam buku “Kisah Pelayaran Abdullah”.
Diceritakan, gelombang yang menerjang jauh lebih tinggi daripada pucuk tiang kapal. Barang-barang terpelanting, air laut menyembur, membuat tubuh para jamaah basah kuyup. Badai yang terus mengganas, seolah tak berhenti. Tak ada yang bisa diperbuat. Abdullah sembahyang sambil duduk berpegang.Garangnya samudera seperti dilukiskan pujangga itu, juga dialami para jamaah haji asal Lombok selama berpuluh-puluh tahun.
Setelah pemerintah menghentikan pemberangkatan haji melalui laut di tahun 1978, cerita tentang kesengsaraan para jamaah dalam perjalanan pun berakhir. Empat hingga enam bulan setelah keberangkatan, sebuah kapal besar nampak di arah barat pelabuhan. Para jamaah yang telah melaksanakan ibadah di tanah suci pulang ke kampung halaman. Pantai Ampenan kembali menjadi lautan manusia. Dan air mata kembali tumpah di kota tua itu.
Mereka yang menangis bahagia menyambut sanak keluarga, para haji yang pulang dengan selamat. Tapi banyak pula terdengar isak duka. Luapan perasaan kehilangan atas orang-orang yang tak akan pernah kembali. (bsm)