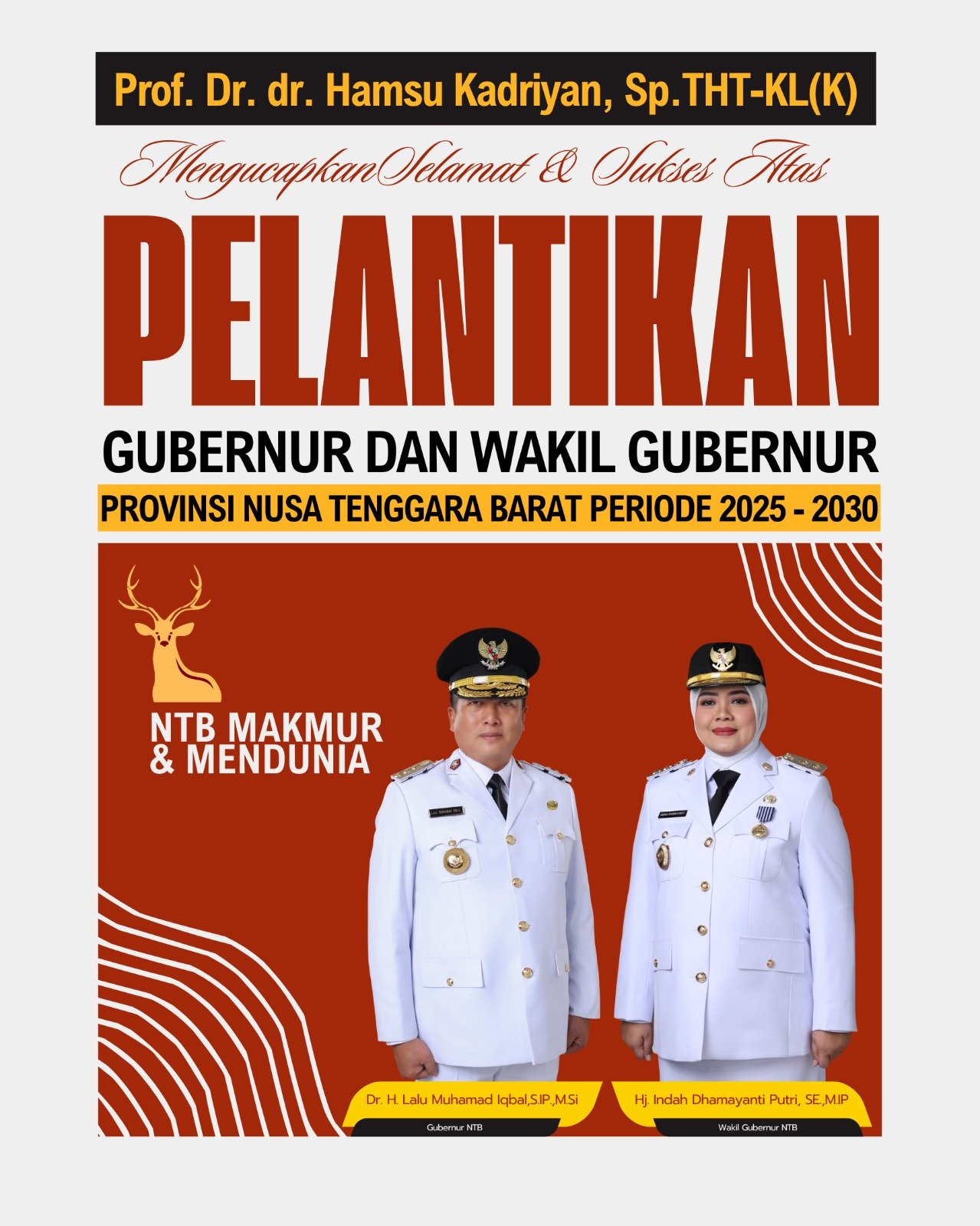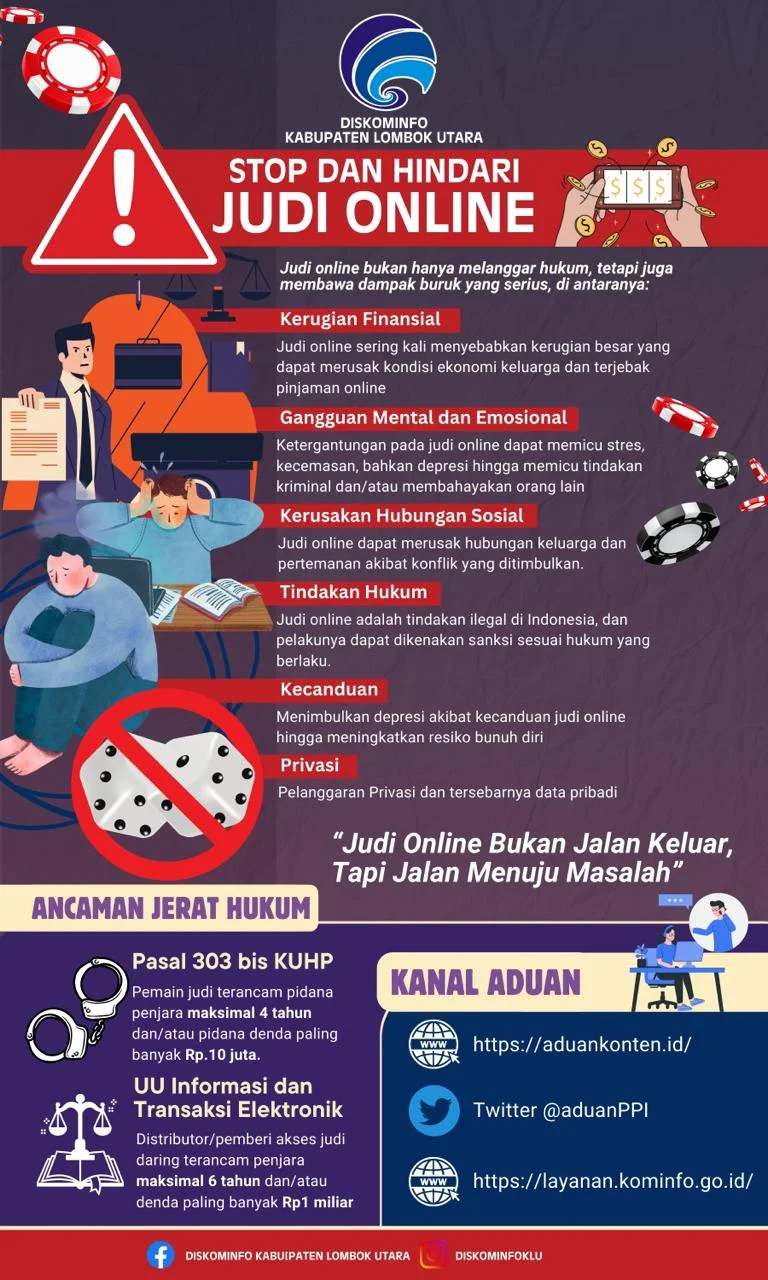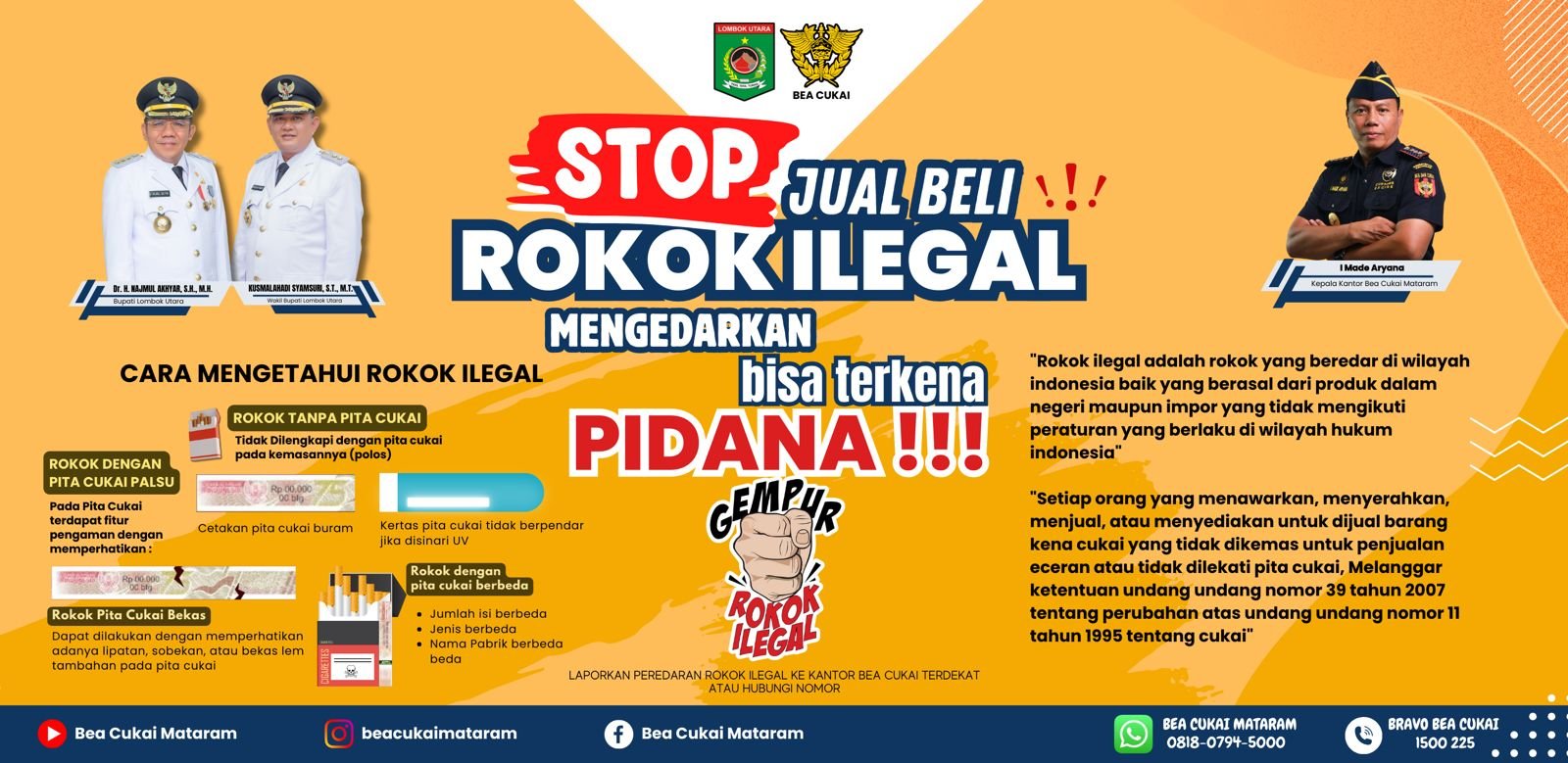Pertengahan 2000-an, sebuah buku yang diterbitkan sebagai salah satu materi muatan lokal (mulok) pembelajaran bahasa Sasak, beredar di sekolah-sekolah di Lombok. Buku itu ditulis menggunakan salah satu varian subdialek bahasa lokal, wilayah asal penulisnya.
Yang kemudian terjadi, respon dari pihak sekolah muncul beragam. Ada yang langsung menggunakannya tanpa persoalan. Ini boleh jadi, para penutur atau pengguna bahasanya, baik guru mulok dan para siswa, berasal dari kelompok dialek yang digunakan dalam buku. Tetapi di sejumlah wilayah, buku itu mendapat penolakan. “Bahasa yang dipakai bukan bahasa kita. Jangankan bagi siswa, kami sebagai guru mulok saja tidak mengerti,” demikian keluhan sejumlah guru mulok ketika itu.
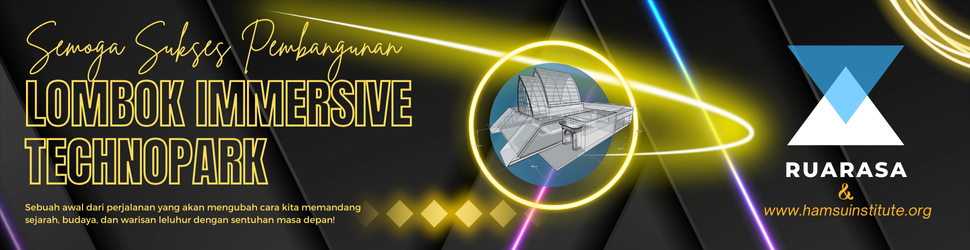
Polemik tentang beredarnya buku tersebut akhirnya diakomodasi Pemerintah Provinsi NTB. Melalui Bappeda NTB yang ketika itu dikepalai Drs Lalu Fathurrahman, M.Sc, terfasilitasi sebuah program spesifik tentang bahasa lokal.
Buku bermasalah itu akhirnya ditarik. “Beliau, penulisnya, bukan ilmuwan. Tidak memiliki basis ilmu pengetahuan tentang bahasa, sehingga beliau menulis hanya berdasarkan intuisi. Padahal untuk membuat materi pembelajaran itu harus ada standar. Sebab nantinya akan ada evaluasi hasil belajar,” kata pakar linguistik Prof Dr Mahsun, MS, yang dihubungi beberapa waktu lalu.
Ternyata, yang mesti “diberesi” tak hanya bahasa Sasak, tapi juga dua bahasa lokal lainnya di seberang Lombok, yaitu bahasa Samawa dan Mbojo di Pulau Sumbawa. “Dua tim dibentuk saat itu. Ada tim yang menjadikan bahasa Sasak sebagai bahasa pengantar, diketuai Dr Husni Muaz. Sedangkan untuk tim muloknya saya yang memimpinnya,” jelas Mahsun.
Bukan kali itu saja lelaki kelahiran Jereweh, 25 September 1959, ini berurusan dengan varian bahasa dan dialekta di provinsi ini. Di tahun 1998, ia terlibat dalam program riset Sasak and Sumbawa Project bersama Prof Bernd Nothofer dan Prof Peter K Austin dari Melborne University. Pada 1997 hingga 2000, ia menjadi peneliti utama pada Proyek Riset Unggulan Terpadu (RUT) Dewan Riset Nasional Menristek dan BPPT. Judul penelitian itu Pengembangan Materi Muatan Lokal yang Berdimensi Kebihinnekatunggalikaan dan Pengajarannya: Penyusunan Materi Pelajaran Bahasa Sasak dengan Memanfaatkan Variasi Bahasa yang Berkerabat.
“Penelitian yang kami lakukan pertama lewat RUT itu hanya 90 desa di Lombok yang kami datangi. Lalu ketika melaksanakan program yang dibiayai Bappeda NTB, kami tambah lima desa lagi, karena ada satu yang tidak muncul. Sebelumnya hanya tiga variasi dialekta: a-a, a-e, e-e. Tidak ada a-o, padahal ada penuturnya di Aik Bukak, Lombok Tengah sana,” lanjutnya.
Dari dua proyek penelitian itu, dengan total 95 desa sampel, akhirnya Mahsun membagi variasi dialek bahasa Sasak menjadi empat kelompok, yakni a-a, a-e, e-e, dan a-o. Jika dirinci, dengan mengambil kata mata sebagai contoh, masing-masing penutur varian dialek tersebut mengucapkannya secara berbeda satu sama lain: kelompok a-a menyebut mata, a-e mate, e-e mete, dan a-o mato.
Lantas, bagaimana dengan ngeno-ngene, meno-mene, meriak-meriku, keto-kete, dan ngeto-ngete? Lima dialek hasil riset Nazir Thohir yang tertuang dalam Kamus Bahasa Sasak yang diterbitkan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 1985 ini mendapat kritik tegas.
Kelima varian itu merujuk pada makna begitu dan begini. Sementara dalam penelitian Mahsun, ia menemukan 24 varian sama yang tersebar di sejumlah titik di Pulau Lombok. Ada beberapa wilayah yang menyebut marak nike, marak meno, marak no, ngano, bro, maning, beka, merene, meriak, meriu, dan ngute. “Kalau kita konsisten menggunakan dua medan makna sebagai variasi dialekta dari kata begitu-begini, semestinya kita mengatakan bahasa Sasak ada 24 dialek, 24 pasangan kata. Mengapa hanya memilih lima? Apa karena kelimanya mudah diucapkan? Itu kritik saya, makanya saya tidak terlalu tertarik dengan pembagian seperti itu,” ungkapnya.
Guru besar FKIP Universitas Mataram (Unram) ini lebih lanjut memaparkan, empat kelompok dalam bahasa Sasak yang dirumuskannya, disebut variasi dialekta. Sebagai ahli bahasa, ia menekankan dialek sebagai penanda bahasa, bukan penanda nama tempat. Keempat kelompok itu mengakomodasi atau mewakili semua variasi dialekta yang ada di Pulau Lombok, yang digiring ke satu asal. Sehingga, “Mata, mato, mete, dan mato, itu ditelusuri dari mana asalnya, dicari Austronesianya, ternyata dari kata mata. Sehingga kita mengatakan variasi ini muncul hanya karena perbedaan tempat saja, dan perbedaan sejarah yang dialami,” papar Mahsun.
Dibandingkan dengan Samawa dan Mbojo yang sama-sama dalam pola dialektal bahasa-bahasa Austronesia Barat, bahasa Sasak jauh lebih rumit. Mahsun menunjukkan peta bahasa yang memperlihatkan tingkat kerumitan itu. Peta bahasa di Lombok ditandai dengan garis isoglos yang tebal dari masing-masing wilayah penelitian. “Sementara di Sumbawa, tingkat ketebalannya ada di bagian barat. Tapi belum sampai pada tingkat dialek. Ada tiga variasi (bagian barat), yaitu Jereweh, Taliwang, dan Tongo, lalu dialek Sumbawa Besar (bagian timur). Ke timur Sumbawa lebih homogen,” ucap Mahsun.
Di Lombok, demikian Mahsun, tidak memiliki lingua franca atau semacam bahasa pengantar sebagaimana yang diterapkan Suku Samawa dan Mbojo. Di Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa, meskipun terdapat lebih dari satu variasi dialekta, namun dalam lawas (salah satu karya sastra Samawa), seluruh penutur dari semua varian menggunakan dialek Samawa Rea (Sumbawa Besar). “Sehingga dialek Sumbawa Besar memungkinkan untuk menjadi bahasa Sumbawa standar,” sebutnya.
Demikian pula di Kabupaten/Kota Bima dan Kabupaten Dompu yang secara umum cenderung lebih homogen. “Meski Dompu dan Bima beda kerajaan, tapi dalam hal kebudayaan mereka tetap memeliharanya. Bahasa mereka satu, bahasa Mbojo,” katanya.
Selain berhasil memetakan tiga bahasa di NTB, Mahsun juga merampungkan materi pelajaran mulok, masing-masing mulok bahasa Sasak, Samawa, dan Mbojo. Materi-materi dalam bentuk buku yang lengkap dengan petunjuk pembelajaran dan silabusnya, untuk tingkatan pendidikan TK dan SD. “Kita bahkan sudah melatih para guru mulok saat itu. Tinggal menunggu perda terbit sebagai payung hukumnya,” jelasnya.
Sayangnya, setelah terjadi pergantian kepemimpinan, dari Lalu Serinata ke Muhammad Zainul Majdi, program yang dimotori Mahsun terhenti. “Kecenderungan di Indonesia itu tidak ada kesinambungan suatu program. Ganti kepemimpinan maka program berganti pula. Ibarat bambu-bambu yang berdiri sendiri-sendiri, bukan menyambung bambu di atas yang sudah ada,” ujarnya.
Itu berarti, ada yang belum tuntas dalam kerangka idealisme ilmuwan sejati. Dan Mahsun masih belum menyerah untuk merealiasikan gagasan-gagasannya merekatkan kembali simbol-simbol kebudayaan yang tersegmentasi, demi keutuhan masing-masing etnik. Keutuhan yang ditunjukkan dengan sebuah identitas kebahasaan: bahasa yang mempersatukan.
Penulis ialah pemerhati sejarah dan budaya Nusa Tenggara Barat